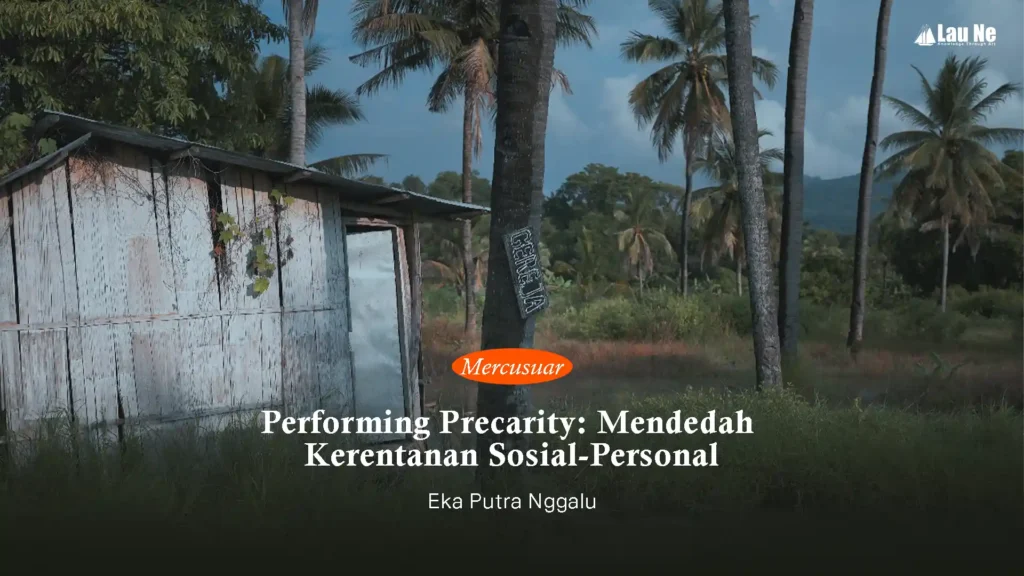We are standing on an always shifting grounds —
Apa yang sungguh-sungguh menopang kehidupan kita hari ini? Apa yang menggerakkan kita hari ini? Masih mampukah kita berharap?
Apa yang kita tatap dan santap sebagai berita hari-hari ini tak lepas dari cerita-cerita kerentanan yang dengan segera memperlihatkan betapa manusia ‘modern’ berdiri di atas pijakan yang selalu berubah, dengan segera berubah-ubah.
Mulai dari Palestina hingga pembakaran berhektar-hektar hutan di Kalimantan untuk perkebunan sawit, mulai dari militerisme yang menguat di Indonesia hingga perang dagang di Cina dan Rusia, semuanya punya pengaruh pada harga minuman keras di club termahal Surabaya hingga harga ikan teri di Maumere, harga vaksin di Jakarta hingga harga gula kiloan di Nabire. Api yang melahap habis kompleks Sukahaji di Jawa Barat, terbakar oleh pemantik yang sama yang membuat warga di Medan mengantri gas elpiji 3 kg. Isu kesehatan mental yang marak merebak di kalangan anak muda digerakkan hantu yang sama yang menggentayangi perempuan dan minoritas gender dan seksualitas yang kerap mengalami kekerasan.
Di Nangahale, Maumere Kabupaten Sikka, gereja katolik berani menggusur rumah-rumah umatnya sendiri. Traktor-traktor memasuki kebun-kebun warga. Orang-orang dengan ikat kepala dan ikat lengan berwarna merah putih, membawa parang-parang panjang, memaksa ibu dan anak keluar dari rumahnya dengan ancaman yang membuat mereka tak punya pilihan. Yang tersisa adalah tubuh-tubuh yang diam, mulut yang membisu. Bahkan doa tak lagi mampu mereka ucapkan sebab mereka tak berhadapan dengan tentara tetapi hamba Allah.
Dalam kasus-kasus ini, kita sedang melihat ada kekuatan ekonomi politik global yang sebenarnya sedang menggerakkan/mengkoreografi kehidupan sosial maupun warga dalam levelnya yang paling kecil: keluarga – personal. Kita bisa melihat apa yang kerap kita sebut sebagai ‘kapitalisme’ sebagai sebuah ‘pertunjukan’ (capitalism as performance) dan adalah pertunjukan (capitalism is performance). Gerak laju orang-orang di jalan raya menuju tempat kerja, traktor-traktor yang melakukan pembangunan adalah ketinampilan yang kerap bersinggungan dengan kapitalisme tanpa disadari kehadirannya. Dalam gestur dan aksi ini, kita bisa membaca kapitalisme sebagai pertunjukan. Dalam hal yang lain, pendewaan atas ekonomi dalam kampanye indeks-indeks pembangunan, semarak perlombaan negara mengukur progres pembangunan dari pendapatan per kapita adalah sebuah pertunjukan yang menampilkan kapitalisme dalam panggung kompetisi global.
Kerap, yang kita pilih sebagai respons atas ketimpangan-ketimpangan ekonomi adalah melawan dengan tangan terkepal, dengan kemarahan yang meluap-luap. Tak salah. Melawan adalah pilihan yang beralasan. Melawan adalah memperjuangkan hak-hak hidup sebagai manusia. Yang kerap tak kita akui, di balik kemarahan itu, selalu ada ketakutan akan kerentanan yang tak selalu terkatakan secara terang benderang. Sebab, kemarahan dan perlawanan lebih sering digiring kepada sebentuk narasi heroisme daripada narasi-narasi kekalahan. Narasi-narasi kekalahan kerap dianggap sebagai antiperlawanan, yang bisa melemahkan perjuangan. Namun, yang sering dilupakan adalah bahkan otoritarianisme paling banal sekalipun menyimpan di dalam dirinya ketakutan akan kerentanan, ketakutan akan kejatuhan.
Performing Precarity adalah upaya melacak ketinampilan ‘kerentanan’ yang kerap terselubung dalam berbagai bentuk: mulai dari tubuh-tubuh yang menderita dan melawan karena penggusuran hingga tubuh-tubuh yang melakukan penggusuran, tubuh-tubuh setengah telanjang di temaram lampu jalan tengah malam, hingga tubuh-tubuh ‘suci’ berselubung jubah keagamaan, tubuh-tubuh buruh harian hingga tubuh-tubuh berbalut seragam birokrat. Setiap tubuh menyimpan kerentanannya masing-masing, sebagaimana setiap fenomena sosial menyimpan kerentanan yang tak dapat dielak.
Upaya melacak ketinampilan ini bukanlah sebuah sikap menyerah melainkan sebuah pilihan refleksi yang bisa dijadikan panduan, visi, cara pandang terhadap masa depan, sebuah gestur untuk merancang serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Menampilkan kerentanan kerap bisa memperpendek jarak antara manusia dengan ketakutan dari lubuk hati terdalam, setiap orang yang kerap tak pernah diakui keberadaannya. Bukan supaya ketakutan itu merasuki kehidupan, tetapi menghantar pada kesadaran akan sistem yang kerap tak adil, kuasa yang semena-mena menindas, dan ideologi yang memenjarakan kebebasan warganya. Performing Precarity adalah upaya membangun ingatan kolektif dan pengalaman sosial, mendorong rasa-merasa (empati) bersama atas pengalaman kerentanan untuk membangun solidaritas antar semua subjek yang rentan: saya dan Anda, tumbuhan dan laut di sekitar kita, komunitas warga yang kita huni hingga dunia yang kita yakini sebagai ruang hidup kita.
Pilihan editorial kali ini lantas dengan sengaja melacak ketinampilan kerentanan dalam tulisan-tulisan yang tayang. Dalam ragam narasi, baik eksplisit maupun implisit, ketinampilan bergerak dan berkelindan, menandai pengalaman personal maupun fenomena sosial yang coba diinvestigasi oleh para penulis.
Tetapi, apa itu Jawa? adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Raymizard Alifian Firmansyah dalam tulisannya berjudul Temanggung sebagai Metode: Lapis-Lapis Kuasa di Jawa Pinggiran. Dalam tulisan ini, kerentanan diperlihatkan melalui pembacaan ulang atas sejarah Jawa yang memusatkan kekuasaan kultural maupun kemajuan pada teritori tertentu yang membentuk polarisasi hegemoni hingga sekarang ini. Polarisasi hegemoni tersebut turut membentuk kartografi urbanisasi yang punya banyak soal terutama ketika tradisi pelan-pelan merengkuh dan merenggut modernitas. Temanggung sebagai sebuah ruang pascakolonial dengan seluruh siasat dan perspektif kewargaannya ditawarkan oleh penulis sebagai sebuah metode untuk membaca perubahan hari ini.
”Kayaknya positioning tetap jadi hal penting, di tengah segala riuh dan gebyar fasilitasi dan festivalisasi yang mengalir deras dari berbagai arah. Mempertanyakan motif dan tujuan mungkin adalah salah satu cara mengecek posisi itu?” Pada rubrik Jala berjudul Mempertanyakan Festivalisasi Kebudayaan Domi Djaga mengkritisi geliat festival di sekitarnya, yang turut ia alami dari dekat. Ia punya keprihatinan atas ekspetasi dan manifestasi yang kurang tepat atas semangat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Baginya, di satu sisi, Undang-undang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan yang kokoh bagi kebebasan ekspresi seni dan budaya, tanggung jawab pemerintah mendukungnya, dan penguatan masyarakat lokal sebagai pelaku dan penggerak kebudayaan. Meski demikian, di levwl implementasi, pemajuan kebudayaan kerap disimplifikasi dalam bentuk festival-festival yang lebih bernuansa seremonial dan berorientasi pada pencitraan atau eksotisasi tradisi lokal. Bagi Domi, fasilitasi pemerintah di bidang kebudayaan dalam berbagai bentuk festivalisasi bisa berdampak menciptakan komodifikasi budaya yang amat berbahaya bagi ekologi dan ekosistem seni budaya di Indonesia.
“Ke mana saja tadi kalian yang lain selama rembug kami? Rubrik Layar berjudul Seraung: Membaca Sungai Seni Samarinda Melalui “Pintu Belakang” memperlihatkan kegelisahan atas kerentanan ekosistem seni yang selalu bergejolak dengan dinamika berlapis. Berkisah tentang konteks Samarinda, kerentanan ekosistem seni ditampilkan oleh penulis dalam hampir seluruh pilihan diksi dan komentar, persepsi dan opini. Tulisan ini bergerak di antara spektrum paranoia dan reparatif yang saling berdialog, meniadakan dan mengadakan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.
Salah apa aku ini? Yeni Yulia Andriani seorang Sunda, menulis pengalamannya tinggal di Papua, dalam tulisan berjudul Kapal Sabuk Nusantara 112 dan Seberkas Nyala di Saubeba. Cerita personal pengalaman penulis yang mengalami kekerasan oleh oknum ketika ia tinggal di Papua dibalikkan oleh pengalamannya yang lain ketika ia bertemu dengan warga desa Saubeba saat menjadi voluntir untuk sebuah program konservasi penyu. Melampaui stigma identitas dan kerentanan yang ia alami secara personal, penulis menyadari adanya ketimpangan yang menciptakan jurang besar pembangunan. Penulis merasakan dirinya hidup dalam privilese ketika tinggal di kota dengan segala kemudahan. Ia tak melihat keharusan konteks lokal menjadi kota, tetapi merefleksikan bagaimana dirinya, tubuh, dan juga kerentanannya dikonstruksi oleh laku urbanisasi. Refleksinya membawa cara pandang yang lebih kritis dalam melihat konteks kultural di Papua sebagai kondisi yang turut dibentuk oleh penguasaan sumberdaya oleh segelintir orang tanpa rasa keadilan.
Pada rubrik Nahkoda berjudul Mussert dan NSB Hindia Belanda di Surabaya, Sarita Diang Kameluh menulis satu wawancara imajiner antara seorang reporter Vereenigd Persbureau dengan Anton Mussert seorang pendiri Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) di Hindia Belanda. NSB adalah gerakan atau organisasi berideologi fasisme yang berbasis di Belanda. Wawancara ini amat menarik sebab diciptakan dari sebuah penelusuran arsip serta pustaka yang cukup teliti dan konsisten. Juga di dalamnya ada perpaduan fakta dan fiksi, berita dan tafsir yang menempatkan sejarah sebagai sebuah horison dengan pintu yang terbuka lebar. Salah satu percakapan yang menarik misalnya demikian:
VS: “Beberapa orang mungkin melihat pandangan Anda ini sebagai semi-rasis. Bagaimana Anda menanggapinya?”
M: “Saya tidak merendahkan bangsa pribumi. Sebaliknya, saya menghormati semangat nasionalisme mereka. Tetapi tanpa arahan, nasionalisme itu bisa menjadi bumerang—bagi mereka dan kekaisaran. Persatuan Hindia dan Belanda adalah fondasi kita, dan jika itu goyah, keduanya bisa hancur. NSB menawarkan jalan tengah: menghormati budaya lokal, dan memastikan stabilitas melalui kepemimpinan Belanda.
Untuk semua fenomena sosial, politik, budaya dan ekonomi yang terjadi hari-hari ini, yang juga ditangkap dan berusaha dijelaskan dalam tulisan-tulisan di laune edisi kali ini, satu jawaban kecil dari Anton Mussert di atas sungguh amat menggelikan: nasionalisme itu bisa menjadi bumerang—bagi mereka dan kekaisaran. Meski menolak dengan tegas kolonialisme, nasionalisme harus tetap kritis diterima sebagai anak kandung dari nasionalisme. Di dalam tegangan itulah modernitas bekerja, menggerakkan pijakan yang benar-benar tidak sepenuhnya benar-benar diprediksi. Guyon Marx: sejarah berulang dua kali: satu sebagai tragedi dan yang lain sebagai komedi. Kita bisa saja jadi aktor dari salah satu atau bahkan kedua babak ini.
Selamat Membaca.