
Kita terlalu sering melihat Jakarta. Salah satu dari banyak alasan mengapa semakin mudah bagi kita untuk meninggalkan televisi dan koran adalah keseragaman konten dan muatannya. Selalu saja Jakarta, atau wilayah aglomerasi sekitarnya, atau paling luas, Pulau Jawa. Hellena Souisa mengumpulkan sampel sepanjang 2014-2015, dan menyimpulkan bahwa Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah empat besar wilayah yang paling sering muncul di program berita. Remotivi, outlet media yang memuat tulisannya, juga meneliti ketimpangan pemberitaan dalam kasus banjir, dan menemukan bahwa perbandingannya menjadi 55,4% untuk Non-Jabodetabek dan 44,6% hanya untuk wilayah Jabodetabek. Dua studi di atas membuktikan ketimpangan pemberitaan yang mungkin hingga kini masih terjadi. Bahkan ketika media memasuki masa digitalisasi.
Bosan dengan Jakarta, saya ingin mengetahui tentang daerah saya sendiri, Kabupaten Sidoarjo, tempat saya lahir dan tinggal kini. Di lingkup nasional, Sidoarjo bukannya tidak punya kekuatan. Sudah hampir dua tahun sejak diadakannya Harlah NU yang mendatangkan presiden pada masa itu Joko Widodo dan Menteri BUMN di kabinetnya, Erick Thohir. Agenda itu menunjukkan signifikansi Sidoarjo sebagai pusat basis NU yang cukup besar di Jawa Timur untuk didulang suaranya dalam politik elektoral. Menjelang Pilpres terakhir, Sidoarjo didatangi oleh ketiga calon presiden: Anies-Cak Imin pada 15 Oktober 2023, Ganjar-Mahfud M.D. pada 21 Januari 2024, hingga Prabowo-Gibran pada 9 Februari. Kedatangan ketiga paslon membuktikan bahwa Sidoarjo memiliki magnet untuk menarik suara ketiga capres dalam kontestasi pemilu lalu. Sayangnya, tidak seperti kekuatannya di nasional, politik lokal Sidoarjo sendiri berantakan.
Sejak awal milenia, Sidoarjo dipimpin oleh bupati korup. Win Hendarso (2000-2010), terjerat kasus korupsi dana kas desa sebesar Rp2,3 miliar. Ia didakwa penjara lima tahun dan denda 200 juta, lalu bebas bersyarat pada 2017. Selanjutnya, Saiful Ilah atau Abah Saiful (2010-2020) menjadi tersangka atas kasus suap pengadaan infrastruktur senilai Rp600 juta dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Banding membuat hukumannya berakhir pada 2022, namun pada 2023 ia dijatuhi hukuman atas kasus lain.
Terbaru, Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor (2020-2024) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pemotongan dana intensif pajak. Angkanya juga lumayan, Rp2,7 miliar. Kasus-kasus ini membuat saya prihatin pada diri sendiri. Bahkan ketika mereka bebas atau masih dipenjara, aktivitas politik mereka masih dimanfaatkan untuk salah satu calon bupati baru.
Warga Sidoarjo kadang secara bercanda menyebut wilayah mereka sebagai “kabupaten auto-pilot”. Artinya, tidak ada sosok pemimpin yang mengarahkan pembangunan dan kemajuan kabupaten ini. “Sidoarjo ben diurus arek-arek,” juga mengisyaratkan bahwa warga Sidoarjo dan anak-anak mudanya siap untuk mengurus daerah ini bahkan tanpa sosok pemimpin. Namun, benarkah begitu? Apakah Sidoarjo memang tidak pernah memiliki sosok politisi jujur yang bisa memimpin dengan amanah? Apakah Sidoarjo tidak bisa melahirkan sosok berintegritas yang bersih dari korupsi?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya mengajak pembaca untuk menengok sebentar sebuah karya visual dari Pameran Lingkar Bermain yang diadakan oleh Serbuk Kayu di Rumah Seni Pecantingan pada September 2024 lalu. Karya yang saya tengok ini berjudul “Terik di atas Bayang-Bayang” oleh Alif Edi Irmawan. Saya akan membahas karya itu di sini.
Lima Spanduk dan Satu Layar
Sebelum melangkah ke deskripsi karya, alangkah baiknya jika saya menjelaskan Pameran Lingkar Bermain. Mengutip dari Pengantar Kuratorial yang ditulis oleh Toriq Fahmi dan Lucky Childa Pratama, “Program Teras Bermain yang dikembangkan oleh Yayasan Serbuk Kayu diinisiasikan sebagai laboratorium untuk mendekatkan seni dengan pendidikan.” Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengembangkan konsep dan metode penciptaan seni sebagai model pembelajaran multifungsi. Terlepas dari muluk-muluknya bahasa birokratis yang dipergunakan, inti dari program ini adalah untuk menciptakan seni yang bisa menjadi media pembelajaran untuk anak-anak sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.
Meski sesederhana itu, Serbuk Kayu rupanya tak main-main. Untuk menghasilkan karya, mereka menjalankan laboratorium ini sejak September 2023 dan bertahap sesuai dengan jargon pamerannya: Gagas-Ramu-Saji. Gagas merujuk pada Saling Bermain yang merupakan ruang untuk saling bercerita dan menulis tentang integrasi seni dan pendidikan. Hasilnya adalah podcast dan zine yang dapat ditemukan di website dan sosial media. Ramu merujuk pada Silang Bermain di mana setiap seniman, guru, atau institusi kebudayaan berkolaborasi dan meramu konsep untuk karya yang hendak ciptakan. Terakhir, Saji, adalah Lingkar Bermain di mana karya-karya itu disajikan dan dinikmati oleh khalayak umum.
Totalnya ada 15 karya seni yang dipamerkan, baik dari seniman, guru, hingga mahasiswa jurusan seni atau pendidikan. Selain itu, Pameran Lingkar Bermain juga menyajikan pertunjukan, workshop, pemutaran film, dan diskusi bersama seniman-seniman yang terlibat. Jujur saja, saya cukup menikmati pameran ini. Selain dekat dengan rumah, saya juga membeli buku bekas murah dari lapak yang tersedia. Workshop penulisan puisi dari majalah bekas juga cukup menyenangkan dan produktif. Saya sendiri menghasilkan satu judul sore itu. Namun, di antara semua karya yang menarik, saya cukup terkagum-kagum dengan karya seni di penghujung rute pameran. Di dalam sebuah rumah joglo yang kusam dan berdebu, ada tiga karya yang dipamerkan. Salah satunya, yang saya sebut di atas, berjudul Terik di atas Bayang-Bayang oleh Alif Edi Irmawan.
Karya ini mengambil cukup banyak ruang dalam rumah joglo itu. Bagaimana tidak, karya ini terdiri dari lima spanduk dan satu layar tancap yang digantung saling bertumpuk satu sama lain. Dari gambarnya terlihat jelas bahwa spanduk-spanduk itu sudah pernah dipasang di jalan, lalu didaur ulang. Irmawan dan kolaboratornya mengecat spanduk itu, melapisi foto-foto pejabat dengan gambar-gambar lain yang lebih menghibur. Sebuah spanduk berlatar kuning dan oranye menampilkan sosok berkumis dengan perut buncit dan logo berbagai partai di jasnya. Di kepalanya terpasang topi toga, namun gelar pendidikannya SD, SMP, SMA, sampai S5.
Spanduk lain dengan gambar perempuan menampilkan wajah penuh bunga, dengan nama “Bunga, S.sn, M.sn, Phd, Mcd, Hai”. Spanduk di bawahnya menampilkan laki-laki berwajah sarang burung, dengan nama “Ir. H. Suket Teki”. Spanduk lain bergambar wajah penuh buah, namanya “H. Buahahahaha, S.H”, dan spanduk lain bertuliskan Waspada (Poli) Tikus dengan tengkorak bertumpuk di bawahnya.
Di tengah-tengah ruangan, sebuah proyektor memutar video stop-motion berisi potongan-potongan berita dan meme. Di bawah tumpukan spanduk yang saling tumpang tindih itu, sebuah spanduk lain digelar di atas lantai, bergambar logo 77 Tahun Kemerdekaan. Dengan latar putih di sekitarnya, para penonton pameran diperbolehkan untuk menggambar sepuasnya, menyampaikan isi kepala dan hati mereka dengan kuas bercat merah. Seseorang menulis “Jadilah Dirimu Sendiri”, yang lain menulis “www slot” untuk menggambarkan kondisi ekonomi terkini yang dikuasai bandar judi. Sayang saya tidak menghadiri pameran ini hingga hari terakhir, sehingga tidak melihat hasil final kreasi pengunjung pameran.
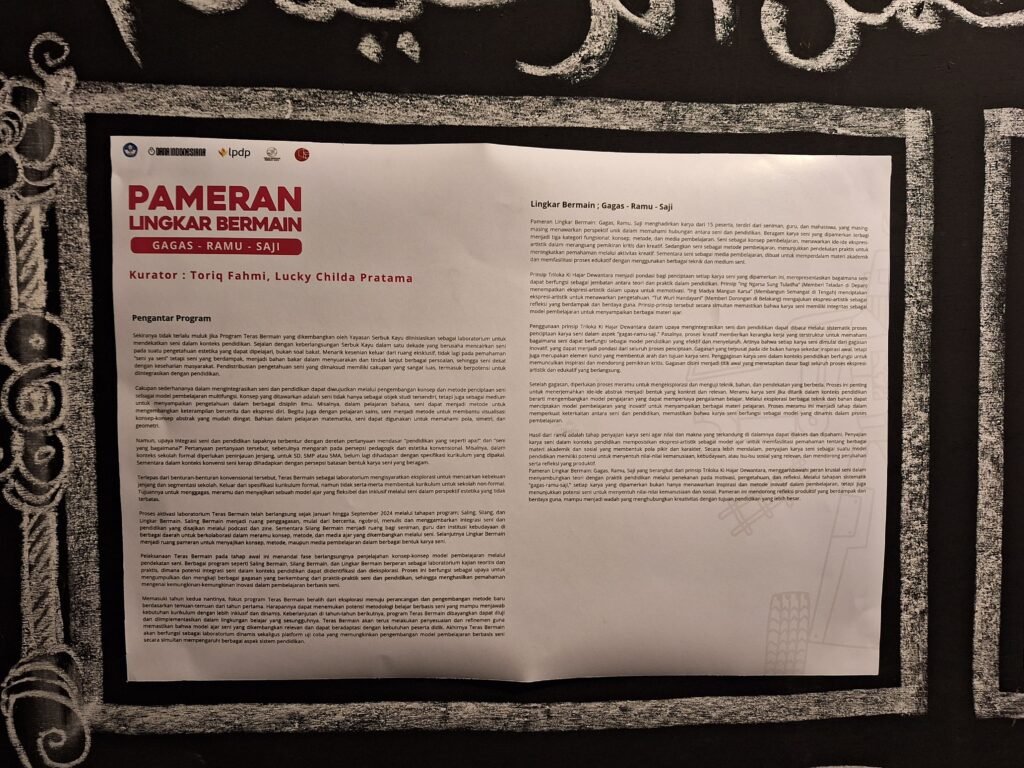
Satire: Mempertanyakan Keberhasilan Pembelajaran Moral
Sebagai program yang ditujukan untuk mengembangkan seni sebagai medium pembelajaran, maka setiap karya dalam pameran ini menyediakan dua deskripsi dalam warna putih dan merah. Putih untuk umum, merah untuk anak-anak. Dalam deskripsi merahnya, panitia pameran menulis panduan,
Teman-teman tahu apa itu korupsi?
Mungkin teman-teman pernah dengar berita di televisi. Korupsi itu perbuatan mencuri yang tentunya tidak baik untuk ditiru. Karena dengan korupsi, banyak orang yang dirugikan dan bisa membuat banyak masalah. Makanya, kita semua harus belajar untuk selalu jujur sejak kecil, supaya saat besar nanti, kita jadi orang yang baik dan tidak melakukan hal-hal buruk seperti korupsi. Karya Kak Alif Edi Irmawan menceritakan persoalan orang-orang yang melakukan praktik korupsi yang tidak patut kita contoh. Ayo, teman-teman, kita belajar jujur mulai dari sekarang!
Sementara penulisan panduan untuk anak-anak ini memerlukan kritik tersendiri, deskripsinya menunjukkan niat sang seniman: bahwa karya itu menunjukkan “orang-orang yang melakukan praktik korupsi”. Namun, benarkah mereka melakukan praktik korupsi? Siapakah sebenarnya orang-orang korup yang dimaksud dalam karya itu?
Deskripsi putih untuk pengunjung umum memberikan gambaran yang tak jauh berbeda, namun sedikit membingungkan. Alif menulis,
Kesuksesan yang berimbang antara pencapaian materi dan pengembangan moral mencerminkan tujuan utama dari pendidikan holistik. Artinya, pendidikan yang baik tidak hanya fokus pada pencapaian akademis tetapi perlu mempertimbangkan pembentukan karakter yang bermoral. Hal ini penting agar kesuksesan yang diraih tidak hanya bersifat material, tetapi juga disertai dengan integritas dan kebijaksanaan, sehingga terhindar dari keserakahan yang dapat mendorong tindakan-tindakan negatif seperti korupsi. Persoalan tersebut yang saya pertanyakan dalam karya ini. Pasalnya, meski pendidikan spiritual yang berbasis pembelajaran moral sudah melekat sejak kecil, tapi kenapa rantai praktik korupsi tidak sanggup diputus? Tampaknya terdapat celah antara teori yang diajarkan dan praktik nyata, di mana nilai-nilai moral tidak sepenuhnya diresapi atau diterapkan. Karya yang saya sajikan ini, menjadi medium pembelajaran satire, yang mengundang refleksi kritis terhadap efektivitas pendidikan moral dan membuka ruang diskusi tentang hubungan antara dampak pendidikan dalam menekan hasrat keserakahan material, sehingga terhindar dari tindakan korupsi.
Singkatnya, karya Alif Edi Irmawan ditujukan sebagai karya satire yang secara ironis dan humoris mempertanyakan keberhasilan pembelajaran moral. Secara humoris, Alif membercandakan gelar-gelar panjang yang selalu dimiliki oleh politisi. Ada yang sampai S5, insinyur, bahkan gelar keagamaan seperti haji. Namun ada ironi di baliknya. Gelar-gelar panjang itu, yang menandakan keberhasilan pendidikan dan ibadah, malah tidak menunjukkan keberhasilan moral ketika mereka terpilih dan menjabat. Praktik koruptif seperti suap-menyuap, menerima gratifikasi, hingga pencurian uang negara mereka lakukan. Pengalaman Sidoarjo sebagaimana disebutkan di awal menjadi contoh nyata praktik korupsinya. Namun, sekali lagi, benarkah Alif Edi Irmawan merujuk pada pengalaman warga di Sidoarjo?
Melampaui Medium: Memperpanjang Umur sebagai Seni Politis
Karya Alif Edi Irmawan mungkin tidak menyebut langsung korupsi berturut-turut tiga bupati Sidoarjo sebagai inspirasi atau kasus khusus untuk karyanya. Semua kepala daerah atau pejabat legislatif punya sejarahnya masing-masing dalam korupsi. Di antara lembaga-lembaga negara, pemerintah kabupaten merupakan pemilik kasus korupsi terbesar, disusul pemerintah desa, pemerintah kota, BUMN, dan terakhir kementerian. Di tahun 2017, korupsi oleh Pemkab mencapai 222 kasus, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1,17 triliun dan jumlah tersangka 326 orang.
Namun, sebenarnya, kepala daerah berada di urutan kesembilan dari 10 besar aktor yang ditetapkan tersangka kasus korupsi. Masih ada ASN, swasta, kepala desa, masyarakat umum, dirut/karyawan BUMN, organisasi/kelompok, aparatur desa, ketua/anggota DPRD, dan terakhir Dirut/karyawan BUMD. Artinya, di antara sekian banyak koruptor di negara kita, tidak semua orang menggunakan alat peraga kampanye seperti anggota dewan dan lembaga daerah. Masih ada orang-orang lain, yang juga tidak kalah pendidikannya, namun tidak serta-merta mencalonkan diri sebagai politisi dan tetap melakukan korupsi.
Sebagai medium pembelajaran anti-korupsi, karya Alif Edi Irmawan sebenarnya populis. Ia menggambarkan ide-ide mayoritas atau masyarakat kebanyakan yang sudah jengah dan muak dengan spanduk-spanduk politisi. Ide-ide yang ia gambarkan sebagai lapisan permukaan sudah ada dalam kepala masyarakat. Artinya, idenya tidak baru. Hanya memang membutuhkan keberanian untuk melakukan itu. Buktinya, karya Alif Edi Irmawan “disembunyikan” di dalam ruangan, alih-alih mengembalikannya di ruang publik sebagaimana spanduk itu berfungsi sebagai alat kampanye. Meskipun, memang ada pertimbangan untuk menaruhnya di dalam karena ada juga pemutaran video stop-motion sebagai bagian dari karya seninya. Namun, bukankah lebih baik jika ditempatkan di ruang publik?
Untuk itu, saya mengusulkan agar Terik di atas Bayang-Bayang tidak berhenti hanya di Rumah Seni Pecantingan, tempat Pameran Lingkar Bermain digelar. Ia mestinya beranjak pada bentuk esensialnya sebagai seni politis, sembari tetap bersifat kolaboratif untuk selalu menjaganya sebagai medium pembelajaran, sebagaimana disampaikan Alfian Bahri (Anon 2024: 8) dalam Pendidikan Melalui Seni: Keindahan Tagore dan Edifikasi Rorty. Seni politis berarti “seni dengan pesan sosial-politik, yang bertujuan untuk lebih meningkatkan serta merangsang kesadaran tentang isu-isu penting dan bermasalah, juga untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam transformasi sosial dan politik” (Lee 2015). Untuk itu, seni politis seperti Terik di atas Bayang-Bayang bisa menjadi permulaan dari kesadaran masyarakat yang kecewa terhadap proses politik elektoral seperti pemilu dan pilkada sebagai proses yang penuh penipuan. Tetapi, juga dapat melampauinya, mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi setiap proses pemerintahan, agar tidak lolos dari proses-proses koruptif yang bisa mengacaukannya.
Ide memperpanjang umur karya itu juga musti dilakukan melalui gerakan. Contoh yang paling relevan (meskipun tidak dekat) adalah gerakan mural di Meksiko yang dimulai sejak 1920-an dan mencapai puncaknya pada 1940-an melahirkan gerakan yang dikenal sebagai “Chicano” pada periode 1960-an. Dalam aspek ruang publik, para muralis dan suporternya terlibat pertarungan dengan pemilik papan reklame (billboard) dengan menggambar pesan-pesan artistik atau politik versi mereka (Reed 2009: 123). Dalam hal isu, para muralis menghabiskan banyak waktu hingga berminggu-minggu mencari lokasi yang cocok untuk mural mereka, sekaligus mempelajari kebutuhan komunitas setempat dan memuat isunya ke dalam karya (Reed 2009: 117). Artinya, kolaborasi mereka dengan masyarakat juga terjalin erat.
Seniman tidak hanya memuat pesan politik mereka sendiri, tetapi juga mempelajari apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar dan mengungkapkannya sebagai isu publik. Dalam karya Alif Edi Irmawan, isu pendidikan dan kegagalan moral itu diungkap. Namun, sebagai perdebatan publik, ia sudah lama sekali terjadi dan tidak membawa keberhasilan.
Untuk itu, alih-alih mempertanyakan kegagalan pembelajaran moral yang individual, saya lebih setuju jika melihat korupsi sebagai kegagalan sistemik yang bersifat struktural. Dalam buku Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi, Sukiyat membagi korupsi dalam tiga macam: korupsi kecil-kecilan (petty corruption) yang dilakukan individu, korupsi kelas kakap (bigger corruption) yang melibatkan pejabat tinggi negara dan korporasi dengan nominal kerugian besar, hingga korupsi sistemik yang dilakukan banyak orang dan dianggap sebagai bagian normal dari sistem.
Sayangnya, kita tidak bisa mengawasi moral yang merupakan hal abstrak sehingga korupsi oleh individu akan terus terjadi. Yang bisa dilakukan adalah dengan bersama-sama bersatu sebagai masyarakat sipil dan mengawasi jalannya pemerintahan agar senantiasa jujur. Dukungan kita terhadap lembaga-lembaga anti-korupsi juga tidak boleh berhenti. Dengan begitu, kita sebagai masyarakat punya peran dalam mengarahkan pembangunan dan kemajuan wilayah kita masing-masing, tempat kita mewariskan seluruh masa depan kepada generasi selanjutnya.
Sidoarjo sendiri tidak auto-pilot. Kabupaten ini mungkin dikuasai orang-orang korup, dari partai yang tidak mau mengakui bahwa tubuh mereka busuk. Namun, masih ada warga-warga dan anak-anak muda yang siap mengarahkan agar kabupaten ini tidak kolaps dan gagal. Dari “Terik di atas Bayang-Bayang” karya Alif Edi Irmawan, saya tidak menyangsikan bahwa pembelajaran moral tetap dibutuhkan. Namun, melalui karya seni ini, partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan proses politik bisa dimulai. Sekali lagi, alih-alih hanya memperhatikan Jakarta dan sekitarnya yang jauh dari kita, alangkah baiknya jika kita mulai bersikap kritis terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal kita yang juga digerogoti korupsi.

Referensi
Anon. 2024. Zine Saling Bermain: Estetika dan Pendidikan. 3 ed. Surabaya: Serbuk Kayu.
Editor: Margareth Ratih Fernandez




