Di sini, waktu melambat Sakuntala
Jika tak bisa dibilang mati
Sementara kangenku memburu-buru
Sedang apakah kau di sana?
Apakah hujan sudah berhenti?
Apakah kali Malini telah tenang kembali?
Apakah cinta kita baik-baik saja?(Sakuntala, Gunawan Maryanto)
Bagaimana Mengenang Maumere? adalah salah satu pertanyaan yang dimunculkan oleh Hananingsih Widhiasri dalam proses diskusi penciptaan karya, saat sedang mempersiapkan pameran bersama Dwi Januartanto dan Komunitas KAHE.
Pertanyaan itu terasa cukup mewakili eksplorasi para seniman yang terlibat selama proses residensi Lumbung Kelana, di Maumere. Di Maumere, Hana yang berasal dari Kolektif Hysteria-Semarang dan Januar yang berasal dari Serbuk Kayu-Surabaya bersama Komunitas KAHE menelusuri situs-situs sejarah juga budaya yang membentangkan ragam isu dan tema, mulai dari sistem pemerintahan lokal, misi gereja Katolik, kolonialisme, kesenian, filsafat, ikonoklasme, komunitas kreatif, pariwisata, suku Bajo, arsitektur, hantu, Tuhan, makan, hingga nasi.
Bagaimana Mengenang Maumere? adalah pemampatan dari pengalaman pertemuan para seniman dengan Maumere yang dilihat dan dialami sekarang, serta cerita, citra, dan artefak-artefak tentang Maumere yang terwariskan dari masa lampau. Pameran ini adalah salah satu bagian/cara para seniman bercerita tentang Maumere dan segala isinya yang mereka alami dalam kerangka waktu sinkronis (saat ini, saat mereka melakukan residensi) dan diakronis (yang terus dihadirkan secara kontekstual oleh cerita, ingatan, dan sejarah).
Residensi Lumbung Kelana sendiri adalah program yang diinisiasi oleh Lumbung Indonesia – sebuah platform bersama untuk kolektif seni yang menghidupi dan dihidupi oleh tradisi dan praktik yang berhubungan dengan lumbung.
Program residensi ini diikuti dan dijalankan oleh 11 dari 12 kolektif seni yang saat ini tergabung dalam Lumbung Indonesia, di antaranya yaitu Serbuk Kayu (Surabaya), Hysteria (Semarang), Pasirputih (Lombok Utara), Komunitas Gubuak Kopi (Solok), Rumah Budaya Sikukeluang (Pekanbaru), Sinau Art (Cirebon), TROTOARt (Jakarta), Komunitas KAHE (Maumere), Forum Sudut Pandang (Palu), SIKU RUANG Terpadu (Makassar), dan Gelanggang Olah Rasa (Bandung).
Selama 14 hari (17-30 Januari 2022) para kolektif saling bertukar peran sebagai tuan rumah dan pengelana, lantas saling belajar dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mengenai kait kelindan antara kolektif seni dan konteks masyarakatnya. Pertukaran dan usaha saling berbagi ini diniatkan sebagai langkah sederhana untuk mengidentifikasi strategi keberlanjutan (sosial-ekonomi-budaya) tiap-tiap kolektif seni dalam konteks masyarakatnya masing-masing juga ekosistem yang lebih luas.
Selama kurang lebih seminggu, Hana, Januar, bersama dengan Megs dan Gee dari Komunitas KAHE mengunjungi Kampung Sikka, STFK Ledalero, Seminari Tinggi Ritapiret, Museum Bikon Blewut, Hubin-Watuliwung, Baba Akong, hingga bertandang ke Kampung Wuring untuk melihat geliat hidup para nelayan suku Bajo dan Bugis di sana. Perjalanan ini sengaja dirancang untuk ditempuh dengan sepeda motor, sehingga memungkinkan para seniman singgah atau berhenti sejenak di tempat-tempat yang ingin mereka lihat dan alami secara lebih bebas.
Temuan-temuan di setiap perjalanan diobrolkan bersama-sama di studio Komunitas KAHE, di sela-sela makan malam, moke, atau ngopi pagi. Secara lebih serius, obrolan mengenai presentasi cerita sepanjang perjalanan residensi ini dibuat dalam mini workshop dengan metodologi penciptaan bersama (collective creation).
Pendekatan penciptaan bersama sedang dipelajari oleh KAHE selama kurang lebih lima tahun terakhir. Mini workshop ini menjadi kesempatan yang baik bagi KAHE untuk berbagai perspektif dan metodologi dalam menghidupi praktik kesenian. Setelah bergulat dengan tukar pendapat dan pengetahuan yang cukup alot, para seniman sepakat untuk membuat pameran.
Sepanjang perjalanannya, ia kerap melihat ikonografi-ikonografi Katolik di berbagai tempat. Baginya, ikonografi Katolik lebih mudah dijumpai dari pada jejak-jejak visual tradisi masyarakat Krowe yang mendiami wilayah Maumere dan Kabupaten Sikka umumnya. Dari yang paling monumental serupa gereja tua Sikka dan patung Maria Bunda Segala Bangsa hingga salib-salib dan arca keluarga kudus yang terpancang di dekat pohon beringin, atau bahkan pintu rumah dan beberapa sudut sekitar studio Komunitas KAHE.
Di Hubin, ia memotret rumah yang masih menampakkan jejak arsitektur kebudayaan Krowe dahulu, watu mahe, dan penduduk-penduduk terutama perempuan yang masih mengenakan sarung dan makan sirih pinang.
Di Wuring, ia melihat arsitektur kampung, cara berpakaian, dan nuansa yang sama sekali berbeda. Orang-orang Bajo di sana seolah tak mengalami yang dialami masyarakat dan peradaban di luar kampung mereka. Mungkin karena mereka distereotipekan sebagai pendatang dan goan. Ia juga melihat tegangan identitas di sana ketika dalam catatannya ia berkisah tentang penerimaan terhadap waria dan sikap kritis Haji Adam terhadap mazhab-mazhab Islam terkini yang kerap bersyiar di kampung nelayan tersebut.
Dalam sketsa-sketsanya, Hana tentu tidak serta merta menampilkan semua kegelisahannya. Sketsa-sketsanya menampilkan gambar-gambar dari realitas sehari-hari, sebuah rumah di Watuliwung, situasi lobi/beranda Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret, atau lanskap perahu di antara rumah-rumah apung di Kampung Wuring. Pada gambar-gambar itu, ia hadirkan sosok-sosok dari masa lampau, seperti Moan Teka pada rumah di Hubin Watuliwung, Yohanes Paulus II pada serambi Ritapiret, atau Haji Adam pada perahu di Kampung Wuring.
Dalam karyanya, Hana merekam citra visual tempat ia berkunjung saat ini, sembari mencoba menghadirkan imajinasi tentang masa lampau pada citra visual tersebut. Sketsa-sketsa ini dibuat berdasarkan amatan dan ingatannya atas tempat yang ia kunjungi dan imaji visual yang ia temukan berdasarkan cerita tentang tempat tersebut.
Dalam sketsanya, Hana mempersoal waktu yang linier sebagai titik-titik lini masa dan waktu yang sirkular sebagai citra mental (memori dan pengalaman eksistensial).
Hana menaruh perhatian yang amat serius pada aspek sejarah, ingatan warga, dan ikon. Eksplorasinya atas sejarah ia masuki lewat ikon-ikon dan bagaimana warga berkisah tentangnya. Ikon-ikon visual-material selalu didialogkan dengan cerita-cerita tentang tokoh dari masa lampau yang terkait erat dan hadir secara signifikan dalam sejarah. Cerita perihal ikon dan tokoh itu kerap ia eksplorasi secara mandiri melalui referensi di internet, juga dalam obrolannya bersama warga kampung, cerita para seniman di KAHE, atau sharing bersama Januar, rekan seperjalanannya.
Kesan kuat yang muncul dari karya-karya Hana adalah dialog yang intens antara sejarah, manusia, dan wujud kebudayaan. Karya-karyanya merepresentasikan perspektif yang kuat bahwa sejarah penting untuk dijadikan basis pengetahuan suatu komunitas masyarakat tertentu agar bisa terus kritis pada hari ini. Karyanya yang luas dan tegas ini dibingkai dalam satu judul yang puitis dan melankolis: Memory of Maumere.
Tidak hanya Hana, Januar pun punya kegelisahan perkara waktu dan eksistensi. Dua tema ini sungguh terwakilkan dalam karyanya.
Januar membuat semacam instalasi lukisan wajah menggunakan cat minyak pada medium tripleks, berbentuk segi empat. Lukisan wajah itu ia pasang pada dua sisi tiang, membentuk semacam kaki, yang kemudian ditancapkan pada tanah. Bersama lukisan yang menyerupai papan baliho pilkada/caleg di kampung-kampung itu, ia sertakan batu-batu yang ada di sekitar studio Komunitas KAHE.
Ada tujuh lukisan yang ditancapkan di tanah, bersama tujuh batu, dengan pencahayaan redup dari lampu pijar berwarna kuning yang diletakkan di atas batu. Jajaran lukisan ini tersebar di halaman studio Komunitas KAHE Maumere.
Pemilihan lukisan dan batu sebagai medium dan bentuk karya Januar bertumpu pada eskplorasinya menge nai kata-kata kunci berikut: watu-pitu, nitu, tuhan-hantu. Secara bentuk, inspirasi membuat lukisan wajah diperoleh dari pengalamannya berkunjung ke museum Bikon Blewut.
Di museum sejarah dan artefak-artefak Flores itu, ia menjumpai lukisan wajah Pater Piet Petu, SVD, peneliti sekaligus kurator pertama museum Bikon Blewut. Cerita-cerita tentang Pater Piet Petu ia dengar dari obrolannya dengan seniman-seniman di Komunitas KAHE, terutama ketika KAHE menggarap karya dan profil Piet Petu di perhelatan Bienale Jogja.
Sosok Piet Petu amat progresif dalam menegosiasikan tradisi (adat, ritus, nilai-nilai) dan modernitas (kolonialisme, pendidikan katolik, teknologi) tidak hanya lewat museum, tetapi juga melalui kuliahnya di ruang-ruang kelas STFK Ledalero, karya-karya pastoral serta laku hidupnya sehari-hari. Lukisan Piet Petu bukan saja menghadirkan citra personal sang pastor belaka, melainkan kenangan akan spiritnya. Piet Petu sudah mati dan kehadirannya sudah tertandai. Ia hanya bisa hidup, jika spiritnya dihidupkan oleh orang pada zaman ini. Januar menemukan spirit itu, pada diri orang-orang yang ia temui dan kemudian ia lukis wajah mereka, sebagai sebuah penanda, sebagai sebuah potret zaman.
Lukisan-lukisan wajah yang dibuat Januar menampilkan orang-orang yang ia temui di Komunitas KAHE, entah eksponen awal berdirinya komunitas ini, maupun orang-orang yang saat ini ada dan bekerja bersamanya dalam pameran. Ia punya keyakinan bahwa KAHE patut ditandai sebagai sebuah gerakan progresif pada zamannya. Entahkah esok atau lusa komunitas ini bubar dan tinggal kenangan, itu tidak jadi soal. Yang pasti, hari ini, saat ketika ia melukis persona-persona yang ia temui itu, mereka telah dan sedang berkarya.
Januar membatasi membuat tujuh buah lukisan dengan tujuh buah batu penjuru menyertainya, sebagai komodifikasi atas konsep pemerintahan lokal pada masyarakat adat suku Krowe yang kerap dikenal dengan istilah Dua Moan Watu Pitu: tujuh tua-tua adat dengan tujuh batu penjuru.
Tujuh buah batu merepresentasi kan batu-batu yang digunakan oleh tua-tua adat sebagai alas duduk, ketika hendak melakukan musyawarah melingkari watu mahe (altar pemujaan), tempat segala perihal kehidupan masyarakat dibicarakan, tempat segala perkara diputuskan, tempat yang imanen dan duniawi, bertemu dengan yang transenden dan ilahi. Bentuk dan material batu yang ia pilih bereferensi pada perjalanannya ke situs Watu Mahe Lepo Pitu di Hubin.
Karya Januar mempertimbangkan dengan serius nilai kolektif kolegial yang berakar pada masyarakat suku Krowe dan menjadi nilai serta pengetahuan yang terus layak untuk dikontekstualisasi. Sejalan dengan yang dilakukan Hana, karya ini seolah ingin bilang bahwa konsep kolektif yang saat ini dihidupi dan dihidupkan oleh Komunitas KAHE juga mungkin kolektif-kolektif lain di Lumbung Indonesia sebaiknya bertumpu pada epistemologi lokal, yang dekat dengan konteks masyarakat setempat.
Jika Dua Moan Watu Pitu yang saling mendistribusikan tugas satu sama lain, mulai dari soal pengudusan (imam) hingga redistribusi tanah sebagai penunjang kehidupan (penjaga tanah), dengan semangat dan prinsip musyawarah mufakat yang dijunjung tinggi, kolektif dalam ranah seni pun perlu sekali menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas.
Yang juga menarik, secara bentuk karya ini juga mengelola sisi-sisi ilahiah/spiritual dari konsep watu mahe, Dua Moan Watu Pitu dan baliho yang lekat dengan imaji politik serta kekuasaan. Jika watu mahe merepresentasikan sisi ilahi, pertemuan Ina Nian Tana Wawa, Ama Lero Wulan Reta sebagai Tuhan, politik kuasa hari ini kerap menjelma demagog, Hantu yang terus membayangi terwujudnya keadilan sosial.
Pada saat yang sama, bentuk karya ini pun persis menghadirkan pemerkaraannya pada waktu dan eksistensi, menceritakan kembali apa yang digelisahkan Hana: bahwa pada suatu masa di berbagai belahan wilayah nian tana, kolonialisme pernah membumihanguskan sejumlah watu mahe, yang serta merta turut menghapus seluruh tatanan nilai, norma, dan kehidupan sosial masyarakat yang menghidupinya sebagai tradisi. Atau, bisa jadi secara amat praktis, karya ini mau bilang bahwa spirit kolektif kolegial selalu akan beririsan dengan pusaran kekuasaan hari ini (neoliberalisme, kapitalisme global). Bahwa, ideal-ideal dalam kolektif akan selalu bergulat dengan kenyataan tentang dompet yang kosong, perut yang lapar, pulsa sekarat, dan skin care yang tak kunjung update. Atau secara lebih ekstrem, kolektif yang paling sosialis pun punya peluang menjadi institusi yang paling kapitalis, ketika kekuasaan menghambat redistribusi modal, potensi, dan peran lantas menciptakan satu penguasa tunggal. Sebuah kolektif bisa menjadi lumbung beras, dan yang lain lumbung emas.
Karya-karya Januar dan Hana menjadi kian terhubung karena keduanya sama-sama memanfaatkan amatan dan ingatan untuk membicarakan saat ini. Amatan berasal dari pengalaman langsung mereka dengan tempat mereka berada dan ingatan berasal dari catatan, rekaman lanskap visual, audio, yang mereka buat dengan bantuan teknologi mekanis.
Dalam perjalanan mereka mengitari Maumere, tubuh dan indera mereka mengalami langsung suasana, bau, suhu, rasa, dari tempat yang dikunjungi. Keduanya pun menggunakan kamera untuk mengabadikan momen, atau menjadikan kamera sebagai medium perpanjangan ingatan (memory extension). Namun, tidak seperti halnya turis yang merekam lanskap dan menjadikannya objek yang eksotis, membuat mereka menjadi kolonial bagi tanah yang mereka pijaki dan potret, Hana dan Januar melanjutkan proses cerapan atas pengalaman-pengalaman mereka dengan melukis. Ada refleksi lebih jauh, melampaui perkara mekanis yang mereka lakukan, yang secara sadar mereka pilih untuk dilakukan.
Jika foto memotong waktu, menjadikan peristiwa kepingan-kepingan mozaik, dan selalu berasal dari masa lampau (Ridho’i, 2022: 105), maka sketsa-sketsa, mural, dan lukisan juga instalasi yang diciptakan oleh Hana dan Januar menyediakan bagi pengalaman mereka durasi, visi yang terus bergerak, dan wacana yang aktual dan terus bisa digulirkan secara kontekstual hari demi hari.
Harapannya, seluruh pengalaman yang diperoleh di Maumere ini terus menerus bermanifestasi dalam bentuk apa pun, dalam proses pengkaryaan yang terus menerus bisa dimulai lantas menemukan jalannya masing-masing. Itulah mengapa catatan yang menyertai pameran ini tidak semata menempatkan ‘karya’ sebagai subjek, tetapi juga ‘diri’, ‘Hana’ dan ‘Januar’. Sebab benar, yang semata hanyalah hanalogi.
Bagaimana Mengenang Maumere? diniatkan sebagai sebuah pertanyaan sekaligus puisi. Sebab dengan tanya dan puisi, ia bisa terus bebas bergerak dalam lintasan ruang dan waktu, menghampiri siapa saja dan tak bakal berhenti menggelitik untuk dipahami. Bagaimana Anda sekalian mengenang Maumere?

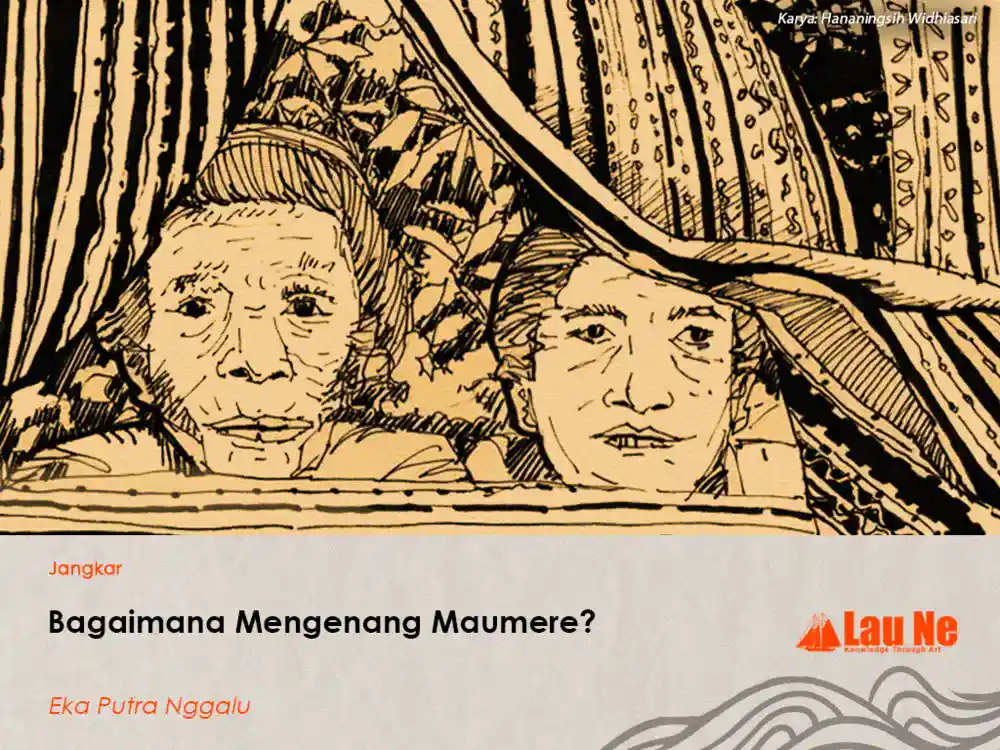



4 Responses
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/ro/register?ref=V3MG69RO
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?