Saya bukan seorang pegiat seni tari maupun pengamat rutin seni pertunjukan. Cukup mengejutkan ketika Juni lalu saya menerima undangan dari Komite Tari DKJ untuk menjadi pengamat sekaligus penulis Benang Merah Festival 2025. Awalnya, saya jujur mengungkapkan bahwa saya tidak merasa mampu. Namun, keasingan saya tampaknya dianggap dapat menjadi titik berangkat yang baik bagi amatan. Tulisan ini, lantas, adalah usaha seorang yang awam seni untuk menceritakan kembali—secara apa adanya—apa yang ia alami dan ‘bawa pulang’ dari jalinan program sepanjang 19-21 Juli kemarin: sebuah pengenalan akan kejamakan kebahagiaan dalam koreografi.
Momen pembukaan festival di panggung bergerak yang dimainkan Street Dance Persaudaraan menjadi kesan pertama saya. Di tengah teriknya siang Plaza Teater Jakarta, gerak-gerik breakdance yang penuh energi memantik sebuah pertanyaan di antara saya dan seorang teman: “kenapa ya, kita gak bisa nge-dance kayak gitu? Kalau gua bisa dance gitu, kayaknya gua bakal lebih bahagia, deh.“
Ada sebuah penghalang yang membedakan antara seniman, penari—yang dianggap sebagai praktisi profesional—dengan publik yang awam, yang tidak bisa menari dalam konteks keahlian serupa. Rasanya, kita yang hanya penonton tidak berhak ikut serta.
Pertanyaan saya juga mengungkap suatu asumsi implisit, seakan ada janji bahwa kebahagiaan dari tari yang sesungguhnya hanya empunya mereka yang bisa ‘menari’ secara profesional.
Kembali ke pembukaan festival, panggung bergerak di mana ia dibuka juga menarik perhatian. Panggung tersebut—dirakit oleh kolektif Gagah Perkakas—berupa papan kayu dua dimensi beroda dengan motif tembok bata merah, pintu yang ditempel miring terkesan asal, bertanda “BAR” besar di tengah dan sangkar burung bertengger di sudut atasnya.
Mungkin begini maksudnya, pikir saya: panggung tersebut adalah representasi potongan kehidupan urban yang bisa diseret ke mana saja, digunakan siapa saja, cair dan mengalir, milik bersama. Begitu pula dengan tari! Sang penari di atas panggung tidak menjadi figur performatif yang berada di atas penonton tetapi justru senantiasa mengajak siapapun yang lewat di sekitar untuk turut bergabung dan naik ke panggung. Panggung tersebut—yang sedari hari pertama hingga hari terakhir festival terus bergerak bersama para penari mengelilingi TIM—seketika membongkar asumsi yang saya miliki di awal tentang tari. Panggung ini pertama-tama membongkar janji kebahagiaan seni yang ‘profesional’ semata.
Saya yang awalnya hanya berniat menonton lantas akhirnya ikut bergerak. Saya berjingkrak kecil mengikuti ritme musik hip hop yang mengiringi, walau kikuk dan tidak tahu apa yang dilakukan. Seketika tubuh saya sendiri ditarik ke dalam suatu koreografi kolektif. Ada suatu kelegaan, pelepasan bahwa tubuh yang kaku ini ternyata bisa turut cair dan bergerak bersama tubuh-tubuh lain. Panggung bergerak tersebut menantang janji kebahagiaan tari yang normatif.
Percakapanku dengan Josh, salah satu penggerak Benang Merah Festival dari Komite Tari DKJ, mengungkap soal paradigma koreografi urban festival ini: melibatkan komunitas, membebaskan tubuh, menjahit program-program sebagai suatu “tenunan” pengalaman kota dan ke-Indonesia-an. Bisa dikatakan, festival ini adalah suatu praksis sosial yang rhizomatiks: bercabang, saling terkait, tanpa pusat tunggal. Ini adalah festival tanpa panggung utama.
Siniar terbuka di siang harinya, bertajuk Kebahagiaan Kolektif, mengajak para partisipan untuk memikirkan kembali ide yang ditawarkan. Saras Dewi, yang juga dari Komite Tari, menyebut bagaimana hari ini konsepsi akan kebahagiaan telah banyak disetir—dikomodifikasi oleh kapitalisme, didikte oleh konsumerisme. Menurut Josh, di tengah hidup yang penuh ketidakpuasan, seringkali ketidakbahagiaan lebih mudah untuk diterka. Eka Putra Nggalu dari Komunitas KAHE Maumere membawa perspektif dari Flores yang disebutnya sebagai singing society, sebuah masyarakat yang dipenuhi nyanyian, pesta, dan perayaan sebagai suatu medium kohesi sosial dan wujud syukur.
Apakah kebahagiaan bisa diukur? Apakah kita perlu mengukurnya dalam suatu indeks tertentu? Demikian pertanyaan yang turut diajukan oleh Hilmar Farid dalam sesi yang sama. Ia menyebut bahwa gerak mendahului bahasa. Mungkin, kebahagiaan memang bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk ditangkap dan diutarakan oleh kata tetapi dialami oleh tubuh yang mempersepsi.
…
Hari kedua dibuka dengan praktik seni yang lebih kecil dan intim. Sahabat kuliah saya, Sophie Trinita, mengadakan sebuah lokakarya zine yang memang sudah cukup lama menjadi hobinya. Kami duduk lesehan di promenade bersama beberapa kawan lain. Sophie membuka lokakaryanya dengan menceritakan bagaimana ia, sebagai seorang seniman visual, terinspirasi oleh bentuk-bentuk perlawanan melalui media mural. Sayangnya, mural sering dianggap sebagai vandalisme dan dapat dengan cepat ‘dibersihkan’ alias dihapus. Bagi Sophie, zine menjadi media untuk mengabadikan ekspresi yang sama. Terlebih, zine juga mudah diproduksi dan disalin untuk disebarkan dalam konteks agitasi dan propaganda.
Ia menginstruksikan kami untuk melipat dan memotong kertas menjadi bentuk buku saku kecil berukuran A5. Kemudian, kami dipersilakan untuk melampiaskan bentuk protes kami mengenai apapun pada kertas-kertas tersebut. Sophie menyediakan majalah untuk dipotong-potong, cat air, spidol warna-warni, pemotong kertas berpola, dan beragam media lainnya. Tidak kalah penting juga, bagi Sophie, adalah peran selotip dalam karya-karyanya yang mewakilkan temporalitas dan kesementaraan. Selotip memungkinkannya untuk bisa memanipulasi dan memindah-mindahkan media karyanya dalam dinamika yang kontinu.
Di tengah-tengah sesi ini, saya sempat bertanya pada Sophie tentang bagaimana ia memaknai kebahagiaan kolektif. Katanya, kebahagiaan kolektif adalah ketika semua orang sudah tidak perlu mengkhawatirkan tentang memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan lantas bisa bebas memikirkan hal-hal lain.
Jawaban Sophie membawa permenungan saya mengenai kebahagiaan pada suatu dimensi yang materialis. Jika kita berbicara kolektif, maka kebahagiaan tidak hanya bisa menjadi tentang sekadar emosi personal. Kita perlu berbicara mengenai distribusi akses terhadap kebahagiaan itu sendiri: siapa yang punya waktu, ruang, dan energi untuk merasakan, atau mengejar kebahagiaan? Bagaimana kebahagiaan bisa dibayangkan di tengah-tengah status quo kita secara kolektif yang dipenuhi oleh berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan? Bagaimana kita bisa bergerak melampaui janji-janji kebahagiaan yang terikat pada kepemilikan?
Saya melihat praktik zine Sophie bukan hanya sekadar media ekspresi tetapi juga perlawanan terhadap janji kebahagiaan yang materialistis, bahwa kebahagiaan ada pada barang atau produk semata. Di sini, justru yang muncul adalah kebahagiaan saling berbagi kumpulan kertas, majalah bekas, dan alat-alat tulis untuk melawan bersama. Sebuah ruang kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Kebahagiaan juga tidak melulu hanya berada pada ruang kosong yang bersih, yang dilukis dengan indah dan rapi. Kebahagiaan juga muncul dari coret-coretan yang asal, yang tidak niat-niat amat, atau bahkan yang ‘tidak pada tempatnya’.
Refleksi saya dibahas lebih lanjut dalam diskusi publik di sore harinya, berjudul Demokratisasi Ruang Melalui Tari. Kennya Rinonce—juga dari Komite Tari DKJ—membuka diskusi dengan satu pernyataan: dalam banyak konteks, akses terhadap ruang bersifat ambigu dan arbitrer. Tidak pernah ada kepastian tentangnya. Ini dibuktikan melalui kesaksian Ibu Mahariah dari Rumah Literasi Hijau, Kepulauan Seribu; yang mengisahkan pengalaman warga Pulau Panggang dan Pulau Pramuka dalam usaha mereka untuk menciptakan, mengakses, hingga merebut kembali ruang-ruang alternatif—dari dermaga, pasar tumpah plaza, hingga hutan pantai—dari rancangan birokrasi dan gentrifikasi.
Menurut Martin Suryajaya, apa yang dilakukan oleh warga Kepulauan Seribu dalam merebut ruang sesungguhnya merupakan suatu koreografi. Ia menjelaskan bahwa tubuh tari adalah tubuh sosial. Sedari dulu kala, tari selalu membawa ekspektasi dan norma sosial: tradisi, ritual, pewarisan nilai-nilai adat, dan lain sebagainya. Tari yang hanya sebagai sekadar ekspresi individualitas, menurut Martin, adalah produk modernitas.
Lantas, ‘koreografi sosial’ adalah suatu usaha untuk membuka kembali tubuh sosial tari dan menghilangkan dikotomi gerak tari antara yang pakar dengan yang awam. Kita harus sadar, menurutnya, bahwa warga awam juga memiliki ekspektasi tentang gerak. Keseluruhan mekanisme dan berjalannya interaksi sosial adalah suatu tarian yang, mengutip Hilmar Farid dari diskusi hari sebelumnya, menjadi suatu ‘ritual koreografi tanpa koreografer.’ Koreografi sosial menjadi sebuah metode meretas gerak tubuh di ruang urban demi mewujudkan kebahagiaan kolektif.
Koreografi sosial tampak nyata dalam gerak-gerik warga yang berulang kali menata ulang tubuh dan sekeliling mereka, merancang perlawanan, menegosiasikan ruang hidup, dan itu semua bukan demi suatu pertunjukan seni performatif melainkan demi bertahan hidup.
Janji kebahagiaan pembangunan para teknokrat runtuh ketika warga sendiri yang harus merajut ulang ruang kebersamaan mereka di tengah-tengah ‘kemajuan’ yang asing. Warga Kepulauan Seribu didorong untuk mengadopsi kebahagiaan yang asing, padahal mereka sudah memiliki kebahagiaan yang lahir dari tubuh, ruang, dan laut yang mereka hidupi secara kolektif.
Di malam harinya, repertoar Torso karya Ayu Permata Sari menjadi sebuah pengalaman yang sangat katartik. Sejak awal, kami para penonton dibagikan masker dan kacamata google medis. Awalnya saya tidak paham untuk apa, sampai saya melihat sebuah lingkaran pasir putih mengelilingi tempat penari berdiri.
Sulit untuk menggambarkan betapa memukaunya penampilan tersebut bagi saya. Torso dibuka dengan proyeksi visual hitam putih yang berantakan ke arah tangga dan fasad utama Gedung Teater Jakarta. Visual tersebut menampilkan Ayu, sang penari, tetapi hanya torso-nya (dari leher hingga pinggang). Di Plaza, Ayu menari di tengah-tengah cincin pasir putih tersebut, di bawah sorotan lampu, dalam harmoni koreografis yang sangat persis dengan yang di proyeksi visual. Saya terkagum-kagum heran.
Ayu memulai tariannya dengan gerak-gerak kecil yang lambat. Tariannya kaku, tersendat-sendat, seperti gerakan robot yang glitching. Musik pengiringnya amat mengagumkan: sebuah campuran antara efek suara tradisional, musik elektronik, hingga beat trap yang membuat saya dan teman-teman ikut menggerakkan tubuh selagi duduk di kursi. Seiring waktu, gerakan Ayu berubah menjadi cepat, eksplosif, seakan ia bukan dirinya lagi. Ia mengurai dan mengikat kembali rambut panjangnya beberapa kali. Kerap kali, Ayu seperti hendak menjatuhkan dirinya pada lingkaran pasir tersebut. Kami tegang, tidak sabar mengantisipasi aksi selanjutnya, benar-benar berada di ujung kursi kami. Kapan ia akan menyibakkan pasir tersebut? Apakah kacamata dan masker kami sudah cukup rapat?
Akhirnya, setelah kurang lebih setengah jam, Ayu merusak lingkaran putih tersebut dan menghamburkannya ke segala arah. Pada saat itu, saya menyadari bahwa pasir putih tersebut sesungguhnya adalah tepung. Ayu menari dan berguling di atas serakan tepung tersebut, berlumuran bersama kami para penonton.
Saya tidak bisa berkata-kata. Torso benar-benar membangkitkan sesuatu dalam diri saya. Untuk pertama kalinya, saya merasakan bagaimana tari benar-benar bisa membuat saya ikut bergerak. Seorang teman bergumam, “ternyata seni masih bisa membuat kita merasa seperti ini.”
Repertoar Ayu membredel janji kebahagiaan normatif akan tubuh—khususnya tubuh perempuan—yang sopan, terkendali, patuh, dan ‘jinak’. Inilah perempuan yang menolak janji-janji kebahagiaan palsu, yang ‘kemarahannya’ justru membuka kemungkinan kebahagiaan yang lebih membebaskan dan benar-benar terasa sejati.
…
Walking Art Lintasan Prasangka yang diinisiasi oleh Ibe S. Palogai dan Aisyah Ardani menjadikan separuh hari ketiga festival dipenuhi oleh keheningan. Bersama banyak kawan lain, kami berjalan dari Taman Ismail Marzuki, naik KRL, dan menyusuri Hutan Universitas Indonesia. Kami diajak untuk tidak berbicara sepatah kata pun.
Sebelum berangkat, kami bersama-sama mendiskusikan prasangka yang paling berpengaruh dalam hidup. Ibe dan Aisyah mengintensikan perjalanan ini sebagai suatu proses untuk menghamparkan prasangka secara terbuka, membalikkan pertanyaan, menanyakan ulang pertanyaan mengenai diri kita sendiri dan sesama. Pengalaman indrawi dari perjalanan diharapkan menjadi proses mengenali diri.
Dari sepanjang perjalanan menyusuri jalanan Jakarta dan hutan kota di perbatasan Depok tersebut, pengalaman paling menarik justru tiba di saat makan siang. Di antara dua trek hutan yang berbeda, kami berhenti di kantin Sastra FIB UI untuk makan siang bersama dalam diam. Anehnya, keheningan itu terasa akrab. Kami rasanya saling memahami tanpa harus berkata-kata. Kami saling menawarkan makanan dan minuman dengan gestur-gestur kecil. Menarik, pikir saya: suatu kebahagiaan dalam perjalanan, kebahagiaan yang tenang dalam kebersamaan tanpa sorak maupun tawa.
Sepanjang perjalanan, saya menggumamkan doa, sebagaimana yang sempat diutarakan jujur di awal: bahwa mungkin, salah satu prasangka terbesar dalam hidup saya adalah tentang keberadaan Tuhan dan suatu makna besar di balik semua ini.
Walking Art ini membongkar janji kebahagiaan produktivitas: bahwa bahagia berarti selalu aktif, selalu bersuara lantang, selalu menghasilkan sesuatu. Padahal, dalam diam dan jeda, dalam doa yang hening dan gumaman hati, saya dapat merasa utuh dan menyatu dengan langkah-langkah sesama saya. Inilah sebuah kebahagiaan yang kecil, yang tidak kasat mata, tidak memenuhi standar produktif, tetapi tetap sangat terasa mengikat dalam suatu solidaritas yang non-verbal.
Malamnya, kami turut merasakan ekspresi kebahagiaan yang sebaliknya. Pada penutupan festival, kami bersama-sama dengan penuh riuh menikmati penampilan Cru Father Said, sebuah kolektif hip-hop dari Maumere. Penampilan tersebut dilanjutkan dengan menari bersama dengan iringan lagu-lagu dari wilayah timur Indonesia. Kami menari dan bersuka ria bersama hingga tengah malam, mengakhiri rangkaian tiga hari festival yang penuh kebahagiaan tersebut. Tubuh-tubuh yang berbeda bersatu, tidak ada penonton vs penampil, hanya lingkaran kolektif yang bersuka ria.
Saya amat gembira ikut menari dalam line dance bersama kawan-kawan yang lain, diiringi lagu-lagu antara lain Siri Pinang dan Ikan Nae di Pante. Tarian saya penuh keraguan tetapi pasti dan penuh tawa girang. Pada momen itu saya melihat intersubjektivitas tubuh yang saling menulari energi. Kebahagiaan yang merasuk dirajut kebersamaan dan solidaritas irama tubuh, hanya berdasarkan fakta bahwa kami hadir bersama—tidak perlu tiket masuk, tidak perlu kepakaran seni, tidak perlu ‘jago’ menari.
…
Bagaimana saya bisa ‘merangkum’ semua pengalaman ini? Bagaimana saya menerka suatu kebahagiaan kolektif dalam koreografi massal ini?
Wacana koreografi sosial dan kebahagiaan sepanjang festival mengingatkan saya pada buku The Promise of Happiness karya fenomenolog feminis-queer Sara Ahmed. Dalam buku tersebut, Sara Ahmed menelusuri suatu genealogi akan kebahagiaan, bagaimana kebahagiaan rasanya selalu hadir sebagai sebuah ‘janji’ yang dilekatkan pada kepemilikan terhadap objek-objek tertentu. Dalam hal masyarakat yang heteronormatif, janji akan kebahagiaan tersebut adalah pernikahan, pasangan suami/istri, anak, rumah tangga; yang menjadi orientasi hidup sebagian besar orang (Ahmed, h. 45).
Namun, di lain sisi, individu-individu yang tidak menempuh jalur yang serupa—misal individu queer atau mereka yang memilih untuk tidak menikah—seringkali dianggap menjadi apa yang disebut Ahmed sebagai ‘alien afek’, mereka yang terasing dan bahkan dianggap ‘merusak’ tatanan kebahagiaan kolektif (h. 49). Lantas, kebahagiaan, bukannya menjadi suatu sensasi pengalaman personal, malah seringkali menjadi suatu ‘teknologi afek’ yang bekerja sebagai perangkat regulasi sosial (h. 44).
Ada beberapa trope figur yang disebutkan oleh Ahmed sebagai contoh para alien afek, mereka yang dianggap sebagai “pengganggu” kebahagiaan kolektif. Pertama, Ahmed menyebut istilah “feminist killjoy” untuk merujuk pada bagaimana para feminis sering dicap sebagai “pemarah” atau “negatif” yang merusak kebahagiaan karena usaha mereka untuk membongkar ketidakadilan di balik “fantasi” kebahagiaan keluarga nuklir (h. 65-67).
Kedua, Ahmed juga menyebut “unhappy queers.” Dalam masyarakat heteronormatif, kehidupan queer dikonstruksi sebagai kehidupan yang “pasti tidak bahagia” karena tidak mengikuti jalur yang pada umumnya (menikah, mempunyai anak). Ahmed mengutip novel Annie on My Mind (1982) karya Nancy Garden dalam menggambarkan bagaimana orang-orang queer seringkali mendengar ungkapan “saya hanya ingin kamu bahagia” yang bersifat normatif: orang-orang queer diarahkan pada model kebahagiaan tertentu, sementara bentuk kebahagiaan lain seperti cinta queer ditolak (hlm. 92-94).
Ketiga, Ahmed menyebutkan sosok-sosok “melancholic migrants,” di mana para pengungsi atau imigran sering dibingkai sebagai “pembawa kesedihan” yang multikulturalismenya membawa beban afektif karena kesusahan mereka dan kesulitan mereka untuk berasimilasi dengan kebahagiaan kolektif yang sudah ada di negara-negara yang dianggap lebih “maju” dan “beradab” (h. 121-122). Kebahagiaan yang didasarkan pada asimilasi rasial lantas “mewajibkan” para migran untuk bahagia degan cara mengadopsi budaya kulit putih (h. 130).
Terakhir, dalam “Happy Futures,” Ahmed melihat bagaimana janji-janji akan kebahagiaan juga memonopoli gambaran tentang bentuk-bentuk kehidupan yang “layak bahagia”—kapitalisme, nasionalisme, heteronormativitas, dsb. Justru, dalam situasi ini, hanya dengan menerka ketidakbahagiaan dan “kegagalan” dalam narasi besar untuk bahagia ini kita memiliki potensi politis untuk membuka tabir, mengungkap ruang bagi cara hidup yang berbeda, untuk menegosiasikan kebahagiaan yang lebih jamak, relasional, dan terbuka pada kerentanan (h. 160-163, 198-203).
…
Sebagaimana tertulis dalam kuratorial festival ini, “Benang Merah” yang terasa bukanlah suatu garis yang mengikat dan membatasi, melainkan garis yang lentur, menjalin, dan menghubungkan dengan keleluasaan gerak. Saya pikir demikian juga dengan kebahagiaan.
Kebahagiaan bukanlah satu jalan lurus yang bisa dijanjikan, apalagi sampai malah mengekang. Seperti yang ditulis oleh Ahmed, jangan sampai kebahagiaan kita malah bergantung pada lokalisasi penderitaan di lokus-lokus tertentu—yakni, bahwa segelintir kelompok harus menderita agar “kita” (yang hanya segelintir) dapat terus berpegangan pada khayalan janji kebahagiaan tersebut (h. 195). Mereka yang seringkali dituduh menolak untuk bahagia sesungguhnya adalah mereka yang sedang meretas ruang-ruang untuk melihat ketidakadilan di balik janji-janji kebahagiaan yang singular.
Benang Merah Festival menghadirkan “kontra-janji” terhadap janji-janji kebahagiaan yang mapan: bukan janji profesionalisme, bukan janji konsumtivisme, bukan janji kapitalisme, bukan janji pembangunan, bukan janji normativitas tubuh, bukan pula janji produktivitas, tetapi kebahagiaan yang cair, bebas, apa adanya, tanpa keterikatan. Festival ini mengajak saya menerka ruang-ruang yang baru: merayakan tubuh yang menari dengan kikuk, zine yang acak-acakan di atas kertas rombeng, ruang yang direbut, tarian yang “meledakkan” bedak ke mana-mana, perjalanan yang hening di hutan urban, dan pesta yang riuh. Bukan garis lurus, bukan “benang merah” pada artian biasanya, tetapi garis yang meliak-liuk ke sana-sini menyingkap kebahagiaan yang dinamis.
Dengan berbagai keriuhan dan kesunyian, kesedihan dan kegembiraan dan berbagai hal di antaranya, festival ini mengundang saya untuk membayangkan kembali janji-janji kebahagiaan. Kebahagiaan tidaklah tunggal, tidak terpetakan, tidak dijanjikan. Ia memang sesungguhnya jamak, relasional, kontradiktif: sesuatu yang tidak akan kita temukan dalam individualitas terisolasi, tapi hanya dalam yang kolektif. Kebahagiaan kolektif, dalam kata lain, mungkin menjadi satu-satunya kebahagiaan yang sudah seharusnya kita bayangkan.
Bagaimana dengan kedukaan kita? Dengan kegagalan untuk bahagia? Biarlah ia menjadi ruang yang menjaga kita tetap sadar akan cara hidup yang lain, untuk kita menenun solidaritas dan resistensi. Kita tidak dipaksa untuk bahagia, apalagi hanya dengan sekadar mengikuti janji-janji kebahagiaan yang diwariskan. Kita diundang untuk menggunakan sepenuhnya agensi kita, untuk senantiasa merasakan, menafsir, dan menjahitnya sendiri dalam ketubuhan kita, temporalitas kita, ke-sementara-an kita, bahkan dalam ketidakbahagiaan kita bersamanya.

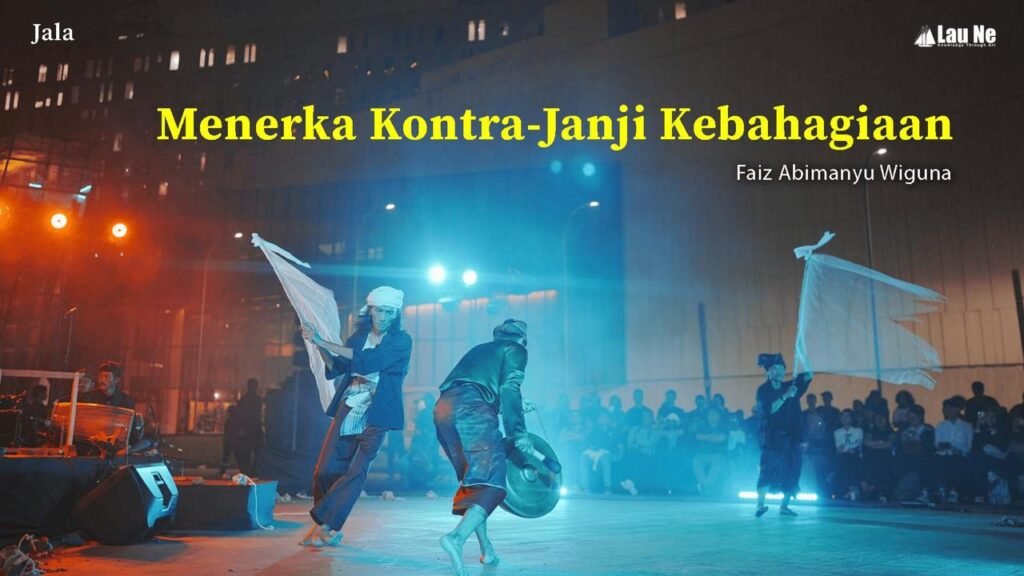



2 Responses
Terima kasih telah membuat dan membagikan tulisan indah ini.