Membangun “Kolektif Berbahagia” di Benang Merah Festival
Benang Merah Festival yang berlangsung pada 19–21 Juli 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, adalah sebuah perayaan warga. Perayaan ini ditopang oleh tiga pilar kuratorial festival: Plaza, Café, dan Re.Kreasi. Salah satu program dalam pilar Re.Kreasi adalah “Kolektif Berbahagia”. Tulisan ini membentangkan proses perancangan hingga eksekusi “Kolektif Berbahagia” dan memperlihatkan bagaimana estetika ruang dalam Benang Merah Festival dapat membangun pengalaman kebahagiaan kolektif di kota dan menawarkan cara lain memaknai ruang festival.
“Kolektif Berbahagia” dirancang sebagai ruang bermain dan bereksperimen. Ruang-ruang ini sering dihimpit, bahkan ditutupi oleh ritme produktivitas kota. Selain itu, “Kolektif Berbahagia” juga menghadirkan pertunjukkan sebagai respons atas berbagai isu kehidupan kota sehari-hari, serta obrolan sebagai ruang pertukaran ide yang santai dan tidak harus selalu transaksional. Karena itu, seluruh rangkaian acara “Kolektif Berbahagia” sejak awal dibayangkan sebagai sebuah laboratorium. Di dalam laboratorium ini, stereotipe, gagasan, citra kota dan warganya diuji coba kembali lewat eksperimen estetika.
Ide mengenai “Kolektif Berbahagia” berangkat dari perspektif koreografi sosial sebagai tema yang mendasari kerja-kerja Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta pada 2024. Dalam dua program Komite Tari, yaitu Artistic Development (Juni 2024) dan Jakarta International Contemporary Dance Festival/JICON (Oktober 2024), Saras Dewi, mewakili Komite Tari, menyampaikan rumusan koreografi sosial sebagai pendekatan kreatif dalam tari yang menempatkan dimensi artistik dan dimensi sosial sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan. Bekerja dengan kerangka koreografi sosial berarti menggali berbagai lapisan makna di balik setiap gerak, dengan memperhatikan konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini juga menyoroti bagaimana tari berperan sebagai medium komunikasi dan transmisi yang efektif untuk menyuarakan perubahan, membangun kesadaran, dan membuka ruang dialog. Koreografi sosial tidak dimaksudkan untuk membentuk narasi tunggal yang kaku atau mengarahkan masyarakat secara sepihak. Sebaliknya, ia berupaya mengenali dan menghidupkan potensi kolektif di dalam masyarakat, menciptakan ruang pertemuan dan kerja sama antarindividu maupun kelompok. Dengan cara ini, koreografi sosial membuka kemungkinan lahirnya tafsir baru yang lentur dan terus berkembang, menghargai keragaman pengalaman serta perspektif, dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses artistik maupun sosial.
Dalam persiapan Benang Merah Festival, “Kolektif Berbahagia” dirancang dengan mempertimbangkan aspek artistik dan sosial. Pelibatan warga kota Jakarta yang terdiri dari kelompok atau komunitas seni dan juga seniman mengacu tidak semata pada relasi yang terjalin secara organik, tetapi juga pada bagaimana kegiatan seni yang diselenggarakan mencerminkan respons atas isu-isu yang terjadi di sekeliling komunitas dan seniman yang juga adalah warga kota. Selain itu, kemandirian pengelolaan kegiatan juga menjadi pertimbangan lain sebab Kolektif Berbahagia dibayangkan sebagai ruang yang dikoreografi oleh partisipannya, bukan oleh kurator atau panitia festival.
Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kolektif Berbahagia yang berlangsung selama Benang Merah Festival 2025 berhasil menggerakkan 2 kelompok warga Jakarta Pusat, 17 komunitas, dan 10 individu yang saling mengkoreografi dan mengorkestrasi ruang festival dalam saling silang partisipasi. Warga Galur, misalnya, adalah juga anggota teater Petra. Salah satu anggota ReEvoluXIIonAir (kelompok alumni S2 IKJ angkatan 12) ada yang berniaga. Sementara itu, salah satu anggotanya yang lain, yaitu Eva Zulfa Ivana (seniman mode) mengadakan lokakarya sustainable fashion. DRKR Kolektif yang mengadakan kelas tari kolaborasi juga menampilkan ‘Sikloths’ (casual outfit for dancer), sementara musisi Ghandiee_ yang menyanyikan lagu-lagu ciptaannya juga menampilkan topi rajut ‘Mushmellow Hats’ buatannya.
Estetika dan Ruang “Kolektif Berbahagia”
Bagaimana “Kolektif Berbahagia” dibangun dan digerakkan mengemukakan perihal negosiasi estetika ruang, sebagaimana perspektif koreografi sosial yang melandasi Benang Merah Festival 2025. Pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini akan berfokus pada ruang, baik ruang fisik, konkret (Kota Jakarta dan segala elemen fisik di dalamnya, TIM sebagai pusat kesenian) maupun ruang abstrak, imajiner (ruang perjumpaan, ruang solidaritas, ruang ekspresi, ruang berbahagia) yang kemudian bermuara pada kebahagiaan kolektif. Karena itu, pembahasan estetika ruang dan negosiasinya yang terjadi dalam “Kolektif Berbahagia” akan dimulai dengan melihat konsep estetika dalam kaitannya dengan partisipan yang terlibat dan aspek artistik dari berbagai aktivitas dalam “Kolektif Berbahagia”.
Braembussche (2009) menawarkan cara pandang terhadap seni sebagai kritik atas cara pandang klasik yang menempatkan karya seni terpisah dengan sejarah dan konteks historisnya. Dalam kerangka Braembussche (2009), karya seni dipandang menempati struktur relasional antara tiga titik utama: seniman, karya seni itu sendiri, dan audiens. Model ini menekankan pentingnya memahami seni bukan sebagai objek yang terisolasi, tetapi sebagai fenomena yang terbentuk dalam segitiga yang terdiri dari intensi dan konteks seniman, kualitas formal-ekspresif karya, dan persepsi serta pengalaman audiens sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.
Socio-historical context
|
Artist → work of art → audience
|
Art historical context
(Braembussche, 2009: 9)
Kelindan karya seni, konteks sosio-historis, dan konteks historis seni yang digagas Braembussche (2009) memunculkan triangulasi konsep dan praktik imitasi, ekspresi, dan formalisme. Meskipun terdapat perdebatan dan kritik terhadap tiga pendekatan ini dalam melihat karya seni, tulisan ini tidak akan berfokus pada pembahasan dan kritik atas tiga konsep tersebut. Bagian selanjutnya akan menggunakan tiga pendekatan ini untuk merefleksikan bagaimana “Kolektif Berbahagia” berjalan dan bergerak selama Benang Merah Festival berlangsung.
Konsep imitasi (mimesis) menyatakan bahwa nilai dan makna seni terletak pada kemampuannya untuk meniru atau merepresentasikan realitas secara utuh. Pandangan ini berakar pada pemikiran klasik seperti Plato dan Aristoteles, yang menempatkan tujuan seni sebagai refleksi dunia luar seniman. Konsep ekspresi menitikberatkan peran keadaan batin, emosi, dan pengalaman seniman dalam karya seni. Seni dianggap sebagai sarana untuk mengkomunikasikan perasaan atau gagasan dari seniman kepada audiens, di mana ekspresi menjadi pusat originalitas dan nilai sebuah karya. Sementara itu, konsep formalisme berpandangan bahwa signifikansi seni terletak pada kualitas formal, misalnya struktur, komposisi, dan susunan unsur-unsur dalam karya, daripada isi atau intensi seniman. Formalisme menyarankan agar seni diapresiasi berdasarkan relasi internal antara elemen-elemennya dan bukan semata-mata pada referensi terhadap realitas atau keinginan subjektif seniman (Braembussche, 2009).
Ketiga perspektif tersebut membentuk fondasi komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi seni, masing-masing menawarkan kriteria unik terhadap apa yang membuat sebuah karya seni bernilai dan bermakna. “Kolektif Berbahagia” sebagai sebuah platform dalam Benang Merah Festival 2025 berjalan dan bergerak sebagai sebuah koreografi yang menampakkan perspektif imitasi, ekspresi, dan formalisme dalam menegosiasi ruang festival dan mengupayakan kebahagiaan kolektif.
Negosiasi ruang dalam “Kolektif Berbahagia”
Tiga aktivitas utama dalam “Kolektif Berbahagia” merupakan imitasi dari realitas kehidupan kota Jakarta: ‘Lab Gerak Kota’ digagas sebagai ruang gerak fisik dan gagasan. Forum ini meliputi lokakarya seni, pajang karya, dan live performance. Lewat berbagai karya seni dan juga penampilan, ‘Lab Gerak Kota’ mengangkat realitas kota dengan segala isu di dalamnya untuk dipertukarkan dengan audiens yang datang ke Benang Merah Festival. Sementara itu, ‘Cuap-Cuap Bersuar’ menjadi ruang percakapan yang berfokus pada bagaimana dinamika kota dan pengaruhnya pada tubuh, gerak, dan kebahagiaan warga kota. ‘Kampung Niaga Ceria’ menjadi ruang unjuk kreativitas yang terwujud dalam berbagai produk kreatif dalam bazar. ‘Kampung Niaga Ceria’ juga menunjukkan realitas seniman yang juga adalah warga kota bertahan untuk hidup dan terus berkarya di tengah kota.
Di tengah kepadatan dan kesibukan kota, keterhubungan emosional dan rasional merupakan tantangan yang sering memisahkan warga dan seniman. “Kolektif Berbahagia” hadir sebagai ruang ekspresi untuk mengkomunikasikan perasaan serta gagasan seniman dan juga menghubungkan seniman dan karya mereka dengan warga dan seniman lainnya. Keterhubungan ini sejak awal diproyeksikan sebagai strategi yang menggerakkan warga kota secara lentur untuk mengimbangi rutinitas yang dihadapi sehari-hari. Kelenturan ini memungkinkan kolaborasi antarelemen “Kolektif Berbahagia.” Pada hari pertama festival, misalnya, kegiatan ‘Lab Gerak Kota’ yaitu kelas tari oleh Explobodies dan LasTeam 689 direkam melalui sketsa oleh komunitas Sketsakti untuk kemudian dibahas dalam sesi ‘Cuap-cuap Bersuar’ bertajuk “It’s All About Lines.” Sebaliknya, pada hari ketiga festival, sesi ‘Cuap-cuap Bersuar’ bertajuk “Bongkar Lab: Tubuh, Gerak, Kota” dengan pembicara Risa Permanadeli, pendiri Sekolah Dua Musim, direspon dengan live performance bertajuk “Esok ‘Kan Ramah” oleh seniman Aulia Detha dan Agata Megumi sebagai bagian dari ‘Lab Gerak Kota’.
Penggunaan berbagai venue di TIM sejak awal disadari sebagai tantangan manajemen ruang yang mesti disiasati. Tantangan ini kemudian dilihat sebagai kesempatan untuk ‘bermain-main’ dengan formalisme ruang dan waktu festival. Lokasi festival di TIM terbentang dari Promenade (di bagian depan) sampai ke Teater Halaman (di bagian belakang). Berbagai kegiatan “Kolektif Berbahagia” memanfaatkan ruang-ruang tersebut dengan prinsip berbagi, termasuk juga menghidupkan ruang yang belum pernah dipakai untuk berkegiatan, seperti taman dan lorong menuju lantai 2 Gedung Planetarium (yang diubah menjadi Warung Lorong untuk ‘Cuap-cuap Bersuar’).
Dari segi waktu, penyusunan berbagai kegiatan dalam “Kolektif Berbahagia” mempertimbangkan keadaan cuaca setiap harinya dan pengunjung TIM pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu/hari pertama dan kedua festival). Pada pagi sampai siang, kegiatan diadakan di ruang tertutup, yaitu Galeri Planetarium, dan ruang terbuka yang beratap, yaitu Promenade, dilanjutkan dengan kegiatan pada siang sampai sore di taman yang dipenuhi pepohonan dan di ruang tanpa atap, yaitu Teater Halaman, Plaza Teater Jakarta, dan Warung Lorong. Kegiatan berhenti sementara saat malam hari ketika ada pementasan di Plaza Teater Jakarta sebagai bagian dari pilar Plaza. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan music performance di Plaza Samping sebagai penutup hari. Di sini, signifikansi artistik dari “Kolektif Berbahagia” berusaha didesakkan lewat struktur dan komposisi lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatannya.
Selain memposisikan tiga pendekatan estetika seni secara linear, pembacaan terhadap “Kolektif Berbahagia” juga bisa dilakukan dengan melihat ketiga aspek estetika tersebut dalam kerangka transmisi. Berbagai kelompok dan individu yang terdiri atas komunitas/kolektif, penari, musisi, maupun perupa, menghadirkan bentuk-bentuk yang berhubungan dengan gerak dalam berbagai konteks. Kepelbagaian struktur dan isi tersebut menjadi wadah bagi beragam elemen yang terlibat dalam “Kolektif Berbahagia” untuk saling terhubung dengan satu sama lain. Keterhubungan ini pada saat yang sama mentransmisi kolektivitas nilai keurbanan.
Kolaborasi antara Dancevelope (Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Tari IKJ) dan Street Dance Persaudaraan (kelompok “baru tapi lama” yang beranggotakan Try Anggara, Abu Grey, dan Dedo Aprilio) pada hari pertama festival dalam ‘Lab Gerak Kota’ bertajuk “TariKota” dapat menjadi contoh menarik. Kedua kelompok ini sama-sama berbasis tari tetapi memiliki latar yang berbeda: satu berakar pada lembaga pendidikan, sedangkan lainnya tumbuh di ruang praktik luar kampus seperti industri dan festival. Relasi keduanya mencerminkan dinamika tarik-menarik antara dunia pendidikan dan dunia praktik yang nyata di kota. Dalam penampilannya, mereka menari tanpa henti dengan pendekatan site-specific, menjelajahi seluruh ruang festival, memunculkan sebuah bentuk ekspresi yang dapat dibaca sebagai upaya menawar keterbatasan ruang.
Contoh lain tampak pada keterlibatan musisi Ghandiee_ dalam kegiatan ‘Kampung Niaga Ceria’ dan ‘Lab Gerak Kota’. Produk topi rajut buatannya, MushMellow Hats, menarik banyak minat pengunjung, meskipun area niaga hanya dibuka pada dua hari pertama festival. Menariknya, saat tampil menutup hari kedua, Ghandiee_ memindahkan display topinya ke samping panggung. Tindakan sederhana ini dapat dimaknai tidak sekadar sebagai strategi praktis untuk berjualan, tetapi sebagai wujud aktualisasi dan kemandirian seniman dalam memastikan keberlanjutan praktik dan karya seninya.
Dimensi kolektif yang bertransmisi dari berbagai usaha negosiasi ruang juga memperlihatkan aspek sosial yang berpijak pada dimensi artistik. Dalam konteks “Kolektif Berbahagia”, seni dapat dipahami sebagai produk sosial yang tumbuh dari interaksi manusia dengan konteks hidupnya, baik dalam dimensi nilai (spiritual) maupun dimensi praktis (pemenuhan kebutuhan hidup). Bila dikaitkan dengan perspektif Koreografi Sosial, “Kolektif Berbahagia” membangun pengalaman interaksi di dalam ruang yang menyerupai simulasi kota, di mana berbagai elemen penggerak festival berperan secara koreografis untuk mewujudkan gagasan artistik mereka sambil terus bernegosiasi dengan ruang hidup dan berkarya yang terbatas. Sejalan dengan pemikiran bahwa Koreografi Sosial mengarah pada gagasan Kebahagiaan Kolektif, muncul pertanyaan lain: Bila Benang Merah Festival merayakan “suar suara warga,” maka dimensi apa dari suar suara tersebut yang sebenarnya dirayakan dalam konteks Kebahagiaan Kolektif?
Eksperimen Estetika Menuju Kebahagiaan Kolektif
Negosiasi estetika ruang dalam “Kolektif Berbahagia” sebagai koreografi sosial mengorkestrasi interaksi antarwarga. Sebagai contoh, pada hari pertama festival dalam ‘Cuap-cuap Bersuar’ bertajuk “Nyusun Lab”, empat kelompok seni pertunjukan yaitu DAN[S]ITY, Kelompok Pojok, DRKR Kolektif, dan Salindia Teater berbagi tentang praktik masing-masing dalam rangka membangun materi kelas kolaborasi. Pada hari berikutnya, kelas kolaborasi berjalan sebagai bagian dari ‘Lab Gerak Kota’ dengan materi yang disepakati bertemakan ‘Beautiful Chaos’, sampai dipresentasikan sebagai improvisation performance saat musisi Ghandiee_ tampil. Contoh lainnya adalah terhubungnya dua kegiatan dalam ‘Lab Gerak Kota’, yaitu kelas puisi oleh seniman Anzar Mustikowati dan mini performance oleh Teater Petra dan Cikini VII Kids yang tidak direncanakan sebelumnya. Kelas puisi diadakan di taman dengan agenda menulis puisi dan pembacaan puisi secara rampak, yang dalam rundown berakhir pada waktu yang berdekatan dengan dimulainya penampilan Teater Petra dan Cikini VII Kids di Plaza Teater Jakarta. Melihat banyaknya pengunjung TIM di sekitar plaza, secara spontan mereka sepakat untuk memindahkan pembacaan puisi ke area tersebut agar puisi karya peserta kelas didengar oleh lebih banyak pengunjung, sekaligus sebagai pembuka mini performance.
Interaksi antarwarga dalam “Kolektif Berbahagia” menunjukkan kolektivitas yang bertransmisi dengan realitas ruang sebagai konsekuensi negosiasi estetika ruang. Di sini, realitas ruang yang bertransmisi menyebabkan perluasan ruang yang terbatas (antar anggota kelompok atau kegiatan), sehingga dapat melibatkan semakin banyak warga. Ini sejalan dengan konsep produksi ruang sosial yang dikemukakan Lefebvre (Wahyudi, 2021). Produksi ruang sosial ini menjelaskan bahwa kolektivitas warga yang dirayakan dalam Benang Merah Festival merupakan cerminan dari ketumpang-tindihan: secara sejarah antara masa kolonial dan pasca kemerdekaan, secara budaya antara tradisi dan modernitas, serta secara kebijakan antara pusat dan daerah. Lebih jauh, “Kolektif Berbahagia” digerakkan oleh daya yang bersifat koreografis untuk membangun harmoni sebagai suatu proses yang berhubungan dengan Kebahagiaan Kolektif. Dari sinilah muncul dimensi pengetahuan sebagai ‘benang merah’ dalam kolektivitas festival, yang tumbuh dari tumpang-tindih interaksi dan negosiasi antarelemen. Ketumpang-tindihan ini bukan dihindari, melainkan disadari dan bahkan dirangkul sebagai bagian dari dinamika kreatif yang melahirkan produksi pengetahuan.
Melalui pembacaan terhadap berbagai peristiwa dan praktik yang berlangsung di dalam “Kolektif Berbahagia”, dapat disimpulkan bahwa Benang Merah Festival mengemukakan suatu temuan penting tentang transmisi ruang, yakni bagaimana kolektivitas beroperasi melalui dan bersama ruang, sembari membentuk kembali makna ruang itu sendiri. Transmisi ini tidak terjadi secara linear saja, melainkan juga melalui berbagai perjumpaan yang bersifat situasional dan tak terduga seperti interaksi spontan antar peserta di bazar, percakapan di ruang diskusi, hingga inisiatif komunitas puisi yang dengan kesadaran kolektif menjadikan diri mereka pembuka pertunjukan teater. Peristiwa-peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa ruang festival bukan hanya wadah representasi, melainkan medan relasional di mana praktik artistik dan sosial saling menegosiasikan bentuk kehadirannya.
Dalam konteks tersebut, Benang Merah Festival menawarkan cara pandang lain terhadap ruang kota yang bukan sekadar untuk dimaknai, tetapi untuk dialami dan dinegosiasikan secara kolektif. Melalui eksperimen estetik yang berpijak pada interaksi sosial dan kebersamaan warga kota, festival ini membuka kemungkinan bagi seni untuk menjadi proses produksi makna yang bergerak menuju kebahagiaan kolektif. Dengan demikian, “Kolektif Berbahagia” dapat dipahami sebagai praktik sosial-estetik yang menghadirkan kota bukan hanya sebagai latar, melainkan sebagai ruang hidup yang senantiasa diperbarui melalui pengalaman bersama, sebagai eksperimen estetika yang berorientasi pada kebahagiaan kolektif. Dalam kerangka inilah, “Kolektif Berbahagia” dapat dibaca sebagai praktik sosial-estetik yang menguji kemungkinan kota menjadi ruang bersama yang terus tumbuh, dinegosiasikan, dan dirayakan.
Referensi
Braembussche, Antoon van den. 2009. Thinking Art: An Introduction to Philosophy of Art. Berlin: Springer.
Kezia, Rebecca. 2025. “Menerjemahkan Kebahagiaan Kolektif sebagai Motif dalam Koreografi Sosial” Jakarta: Benang Merah Festival.
Wahyudi, Agus. 2021. “Memahami Konsepsi Produksi Ruang Henri Lefebvre” Antologi Teori Sosial (Ed. Fitri Mutia). Surabaya: Airlangga University Press. Hal: 211-235.

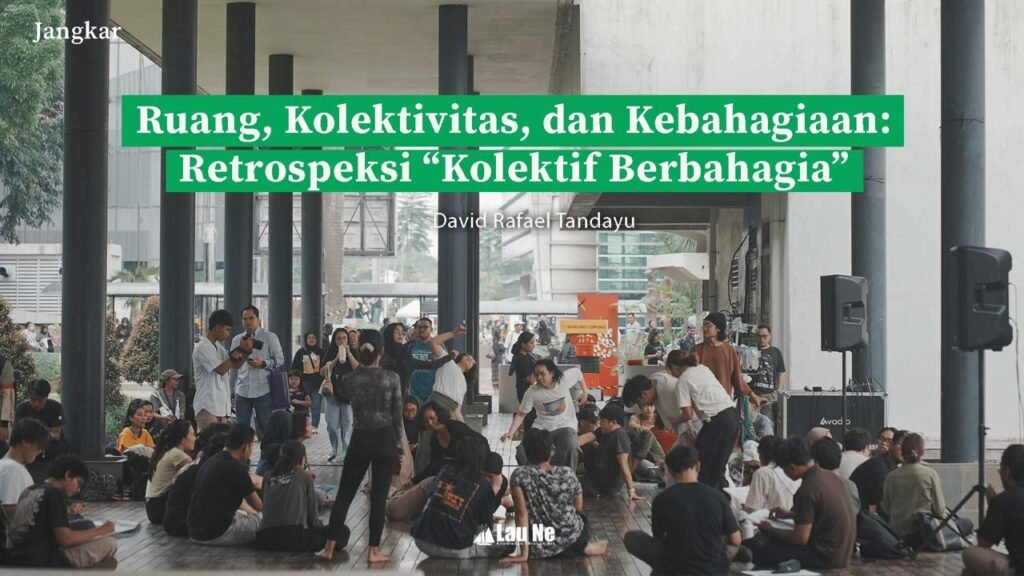



satu Respon