Pertanyaan itu berangkat dari kenyataan yang tampak dalam social performance warga. Terutama dalam berbagai perayaan ritual tradisional, kita bisa melihat tubuh-tubuh warga menempuh perjalanan ulang-alik: ke masa silam sekaligus masa kini, di masa kini sekaligus ke masa depan. Di Gresik, misalnya, ada perayaan tradisi tua bernama Sanggring Kolak Ayam Gumeno. Perayaan itu berusia 500 tahun, merawat sebuah jamu kolak ayam warisan Sunan Dalem (anak Sunan Giri) yang dititahkan kepada para santrinya. Dalam perayaan itu, yang bertepatan dengan malam 23 Ramadhan, warga laki-laki (sebagai representasi santri) Desa Gumeno di Gresik akan memasak dan menyuguhkan kolak ayam sebagai menu berbuka puasa bagi seluruh pengunjung yang datang. Gerombolan laki-laki memasak menu yang sama di tanggal dan bulan yang sama selama 500 tahun adalah pertunjukan kolosal masa silam yang menubuh. Dalam Sanggring Kolak Ayam Gumeno apa yang disebut “tradisi”, bahkan mungkin “sejarah”, merasuk dalam kerja tubuh memasak dan makan, dipentaskan di panggung sosial bernama desa, lalu turut menjadi agenda pariwisata Gresik hari ini. Itu artinya, koreografi tubuh warga Gumeno bisa ditatap dalam dua gerak simultan: kembali menuju ingatan masa silam sekaligus meneguhkan kepentingan masa kini.
Dalam peristiwa preservasi tradisi/sejarah itu pun, warga punya gerak tubuh lain yang tak sepenuhnya berbasis pada masa silam: berjualan jajanan modern, seperti kebab, sosis panggang, bahkan Korean seafood. Tentu saja yang terakhir itu tak benar-benar dari Korea, menyerupai penganan laut Korea lebih tepatnya. Karena memang bukan makanan berat, kolak ayam Gumeno tak cukup ampuh menambal lapar. Jajanan modern jualan warga itulah yang menyokong ketahanan lambung para pengunjung, terutama yang datang membawa anak-anak. Jajanan modern ini dijual tentu saja karena financially proven mendatangkan cuan. Artinya, ada secercah harapan atas terpenuhinya kebutuhan hari esok pada setiap corncow (dog haram soalnya), topokki, kebab, dan sosis yang dijual. Kenyataan gamblang ini menunjukkan betapa tubuh warga adalah mesin waktu yang tak bisa dikunci arahnya. Gerak tubuh mereka bisa menghadirkan masa silam, meneguhkan masa kini, sekaligus merengkuh masa depan.
Saya menyaksikan hal serupa di banyak tempat dan peristiwa lain: jathilan di Bantul, jaranan di Temanggung, tayuban di Pacitan, wayangan di Rembang, rokat di Madura. Semuanya menunjukkan pola yang sama. Tubuh masa kini warga yang bertungkus-lumus menghidupkan masa silam selalu juga mencari jalan ke masa depan, dan mereka melakukannya dalam satu tarikan napas. Saya pernah menatap seorang pesinden yang khusyuk melantunkan tembang tradisi; satu tangannya memegang mik, tangan lainnya menopang live Tiktok di layar ponsel. Dan tak satu pun warga berminat jadi kritikus budaya untuk sekadar memprotes peristiwa itu. Semua berlangsung begitu saja, apa adanya. Tubuh yang menyuarakan masa silam sekaligus menyongsong masa kini dan masa depan.
Kenyataan itu mengingatkan saya pada Frantz Omar Fanon, seorang filsuf dekolonial yang lahir di tanah jajahan Prancis. Pada 1952, Fanon menerbitkan sebuah buku berjudul Peau noire, masques blancs (diterjemahkan menjadi Black Skin, White Masks pada 1967). Ditulis dengan gaya autoetnografis, buku itu mendedah bagaimana kolonialisme bekerja pada orang-orang kulit hitam. Perasaan inferior dan insekyur, menurut Fanon, menubuh dalam diri orang-orang kulit hitam akibat sejarah panjang perbudakan. Tak peduli seberapa nyetelnya orang-orang kulit hitam dengan gaya hidup bangsa kulit putih, orang kulit putih akan selalu melihat kulit hitam lebih rendah. Cara berpikir inilah yang menopang kolonialisme; sebuah penginstalan ingatan baik dalam tubuh penjajah maupun tubuh terjajah. Tubuh-tubuh terjajah berlomba untuk menjadi seperti para penjajah mereka, melalui pendidikan, bahasa, dan status simbolik. Tubuh-tubuh berkulit hitam berlomba memakai topeng putih. Tetapi, itu soal tubuh-tubuh yang terjajah. Apakah penjajahan sebagai masa silam niscaya bekerja demikian pada tubuh-tubuh pascakolonial? Bagaimana tubuh-tubuh pascakolonial itu menawar masa silam, masa kini, dan masa depannya?
Terbitan Lau Ne edisi kali ini bisa dibaca melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Secara umum, tulisan-tulisan yang terhimpun banyak bicara soal tubuh, baik tubuh personal maupun tubuh sosial. Eka Putra Nggalu memulainya dengan Apa yang Tersisa dari Masa Depan? di kolom Jangkar. Catatan kuratorial program residensi Pseudo-Entertainment #1 itu menawarkan kemungkinan eksplorasi tubuh atas Bandung (sebagai lokasi program) melalui percakapan Tamara Soukotta dan Rosalba Icaza. Bagi keduanya, tulis Eka, Bandung bukan hanya ingatan beku atas Konferensi Asia Afrika sebagai gestur dan gagasan dekolonial dalam politik global. Bandung juga adalah taman purwarupa refleksi diri. “Hari-hari ini, menempatkan Bandung sebagai upaya merefleksikan diri sendiri (self-reflexivity) rasa-rasanya adalah juga sebuah pilihan politis,” tulis Eka. Selanjutnya, Eka juga menulis Kartografi Sosial dan Estetika (dalam) Jaringan untuk memapar proses residensi secara lebih komprehensif. Tulisan itu bisa dibaca di kolom Layar.
Masih di kolom Jangkar, pada tulisan Kota Dalam Teater: Cermin Tubuh-Tubuh yang Dibungkam, Andi Batara Al Isra mendedah bagaimana tubuh, kota, dan teater saling bertukar-tangkap melalui program Kota dalam Teater di Makassar. Program yang diinisiasi Kala Teater itu menyuguhkan beberapa pertunjukan selama empat hari berturut-turut. Pertunjukan-pertunjukan representasional itu, dalam catatan Andi, melibatkan tubuh yang beragam: warga, kelas pekerja, perempuan, bahkan lanskap dan infrastruktur kota sendiri sebagai tubuh urban (corporeality of the urban). Melalui refleksi atas gerak kontemporer, gerak situasi yang berlangsung kini dan di sini, tubuh-tubuh itu menempuh perjalanan ulang-alik atas ingatan gestur masa silam mereka dan kerentanan hari ini sebagai potensi trauma bagi masa depan.
Di kolom Layar, S. Sophiah K. dan Amina Gaylene mengajak kita menyelami koneksi tubuh personal dan tubuh sosial. Sophia menulis Dari yang Menggunung, Kembali ke Hidung: Catatan Residensi Festival Bantargebang 2025. Ini adalah catatan personalnya tidak hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai manusia yang mengalami Bantargebang. Menariknya, Sophiah mengulas bau sebagai ingatan yang menubuh atas sejarah komunitas. Bau yang terhidu pada tubuh personal menyimpan ingatan atas riwayat tubuh sosial. Dalam tulisannya, Apakah Bapak akan Tetap Memegang Tangan atau Pundakku Jika Pasarnya Sesepi Ini?, Aminah merefleksikan pengalaman tubuhnya ketika berhadapan dengan Pasar Sarijadi di Bandung. Ia memulainya dari ingatan yang sangat personal: pergi ke pasar bersama bapak. Di Pasar Sarijadi, ingatan personal yang menubuh ini ‘berdialog’ dengan gestur para pedagang. Setelah Pasar Sarijadi direvitalisasi, koreografi tubuh para pedagang (juga pembeli) tak lagi sama. Amina mengajak kita memikirkan ulang bagaimana tubuh warga terkondisikan dalam ruang publik bernama pasar. Ingatan masa silam dan harapan menjalin tegangan di sana, di ruang yang selalu kini. Masalahnya, itu ingatan siapa? Itu harapan siapa? Warga atau penguasa?
Ruhaeni Intan menelusuri tubuh yang kesepian di kolom Jala. Ia menulis Adakah Jalan Keluar untuk Membebaskan Diri dari Belenggu Kesepian? sebagai oleh-oleh catatan lawatannya ke Jepang. Membandingkan pengalamannya di Moriya dan Yogyakarta, Intan menelusuri kesepian tidak hanya sebagai pengalaman tubuh personal, melainkan juga sebagai gejala tubuh sosial. Secara personal, seseorang mengalami kesepian ketika meninggalkan/ditinggalkan; artinya kesepian adalah implikasi atas pergeseran diri dan tubuh. Kesepian terjadi ketika sesuatu telah menjadi silam. Rasa kesepian yang dialami seseorang, terutama di kota modern nan kapitalistik, adalah sebentuk keterasingan diri pada segala yang kini dan di sini. Jika kita merenungkan tulisan Intan secara saksama, kita akan mendapati suatu kenyataan yang bersifat lintas: kesepian karena modernisasi dan kapitalisme bisa menyergap siapa saja di mana saja. Dalam hal ini, Jepang dan Indonesia tidak hanya terhubung oleh sejarah kolonialisme, tetapi juga oleh tubuh-tubuh yang duduk terdiam dengan tatapan kosong di bangku taman sepulang kerja.
Masih di kolom yang sama, Latief S. Nugraha menulis Ia sedang Memisahkan Otniel Tasman dengan Lengger. Latief mencatat pertunjukan Otniel Tasman, seorang koreografer sekaligus pelaku lengger asal Banyumas. Pertunjukan itu mengupas lapis-lapis dimensi tubuh personal Otniel dan tubuh lenggernya. Lapis-lapis itu tak sepenuhnya mudah dimengerti, bahkan mungkin oleh Otniel sendiri, sebagaimana kita tak mungkin mengerti diri kita sepenuhnya. Barangkali karena lapis-lapis itu membawa kita pada perjalanan ulang-alik antara yang dulu, kini, dan nanti, antara yang di sini dan di sana. Latief, misalnya, menulis:
“Otniel Tasman memasukan hal-hal di luar panggung lengger, menjadi suatu (per)ingatan atas tubuhnya yang terbuka. Betapa kompleks lapis-lapis garis yang dibuat, saling menjalin satu sama lain. Terdapat memori akan pengalaman masa lalu dan visi utopis tentang yang ideal di masa depan. Ada ekosistem yang bekerja. Karenanya, mungkin, identifikasi terhadap tubuh menjadi bermasalah, sulit dimengerti oleh dirinya sendiri. Karenanya, iring-iringan peristiwa: segenap ketidaktahuan, sekalian kemungkinan, dan seluruh paparan terhadap tubuh, membutuhkan ruang percakapan. Dengan demikian, keterkejutan personal maupun komunal yang muncul dan hidup di tubuh Otniel Tasman bisa dibagi dan diterima oleh dirinya sendiri dan bersama-sama.”
Dalam tulisan Latief soal Otniel, sebenarnya kita bisa melihat tawar-menawar antara diri, tubuh, dan kuasa di luar diri. Tak selamanya diri dan tubuh sepenuhnya merdeka. Pun tak selalu kuasa di luar diri datang untuk membungkus dan menindas. Kadang, keduanya berjumpa untuk bercakap-cakap, tentu dalam berbagai bentuk yang mungkin. Dan percakapan itulah yang membuat kita bisa bertumbuh, baik sebagai diri personal maupun sebagai bagian dari komunitas sosial. Ini tentu menantang pikiran jumud bahwa diri niscaya harus merengkuh bebas sepenuhnya dan kuasa kolonial adalah setan belaka! Ah, emangnya iya? Tak mungkinkah diri ini mengkoloni tubuh kita sendiri, atau sebaliknya?
Sebagai pamungkas, Amanatia Junda mengisi kolom Nahkoda dengan percakapan bersama Sakdiyah Ma’ruf. Bagaimana Sakdiyah Ma’ruf Menghidupi Ruang Tawa sebagai Perlawanan? adalah dialog yang membuka banyak kemungkinan. Obrolan Amanita dan Sakdiyah mengalir dari soal ruang dan gerakan alternatif yang mempertimbangkan pengalaman tubuh perempuan, soal identitas diri yang bercabang, hingga soal posisi komedi sebagai agensi perlawanan. Barangkali, ini bukanlah percakapan yang tuntas. Bagaimanapun juga, Sakdiyah adalah diri dan tubuh yang masih menempuh jalan. Apa yang bisa kita baca dari pilihan-pilihannya saat ini adalah bagian dari perjalanan tubuhnya, baik sebagai komedian perempuan, sebagai istri, maupun sebagai bagian dari berbagai lapis komunitas sosial. Dan perjalanan tubuh itu belumlah usai.
Ketika membaca seluruh tulisan di edisi kali ini hingga tuntas, kita bisa membayangkan gerak tubuh kita sebagai jalan dengan banyak ruas. Setiap ruas bisa mengantar kita pada tikungan waktu yak tak tertebak: ke masa lalu atau menuju masa depan. Bekas gores luka, misalnya, bisa mengingatkan kita pada suatu gerak yang pernah silam, juga mengingatkan kita pada suatu hasrat yang hendak direngkuh saat nanti. Atau, apa persisnya yang sedang tubuh kita tempuh saat ini? Ke manakah kita hendak menuju? Kalau ke masa lalu, yang seperti apa? Jika ke masa depan, yang semacam apa? Seluruh tulisan di edisi kali ini tak sedang menawarkan destinasi tujuan, tetapi hendak menjadi rekan seperjalanan.
Jadi, mau ke mana? Siapa tau searah.

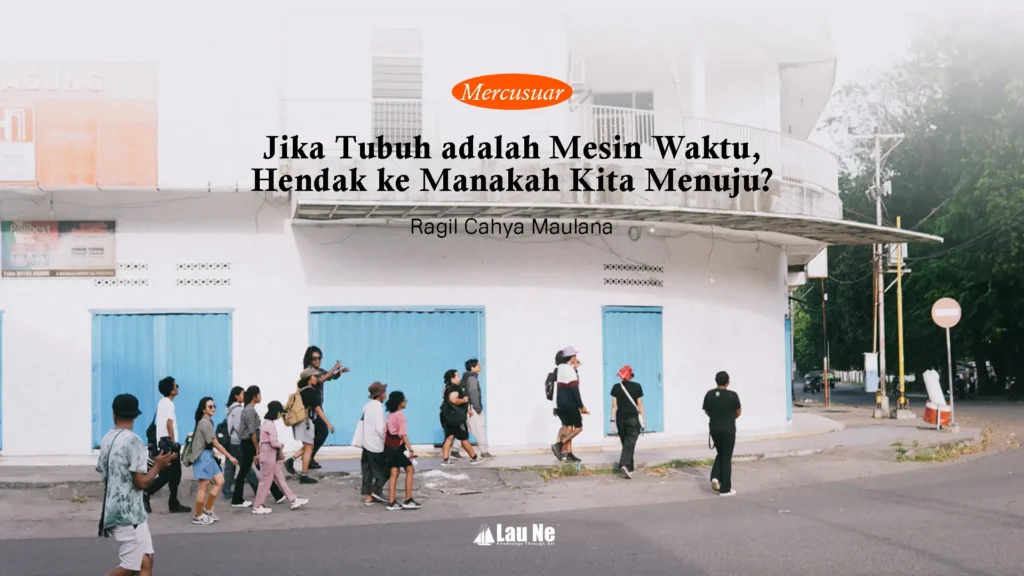



5 Responses
Interesting read! Understanding variance is key in any game of chance, and platforms like 77jl online casino are making access easier. Streamlined registration & apps are smart moves for player experience!
Interesting points about responsible gaming! Seeing platforms like jollyph game prioritize security-KYC & 2FA-is a smart move for building player trust & a sustainable ecosystem. It’s key for long-term viability!
Basic strategy really shifts your perspective! Seeing how even small decisions impact the game is fascinating. It reminds me of platforms like superph22 app download, where understanding the rules is key to enjoying the experience-and winning, of course! A solid foundation helps a lot.
I enjoyed reading this article. Thanks for sharing your insights.
That’s a great point about balancing tradition & tech in modern gaming! Platforms like phfiery app download apk really seem to get that, building on the Philippines’ rich gaming history. It’s cool to see that evolution! 👍