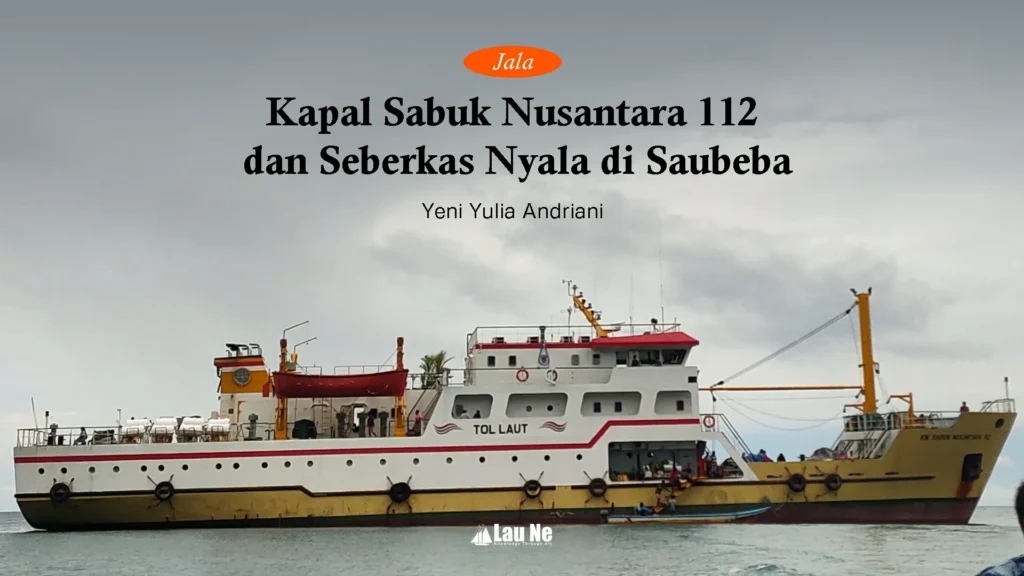Tanah Papua tanah yang kaya
Surga kecil jatuh ke bumi
Aku adalah perempuan Sunda yang jatuh cinta pada lirik lagu “Tanah Papua” oleh Edo Kondologit itu. Setelah lulus studi S2 dari sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, aku memilih bekerja sebagai dosen di Manokwari pada 2019 sekaligus menjemput impian menjelajahi surga kecil yang jatuh ke bumi. Aku ingin melayari jernihnya biru laut Papua yang selama ini hanya kutatap melalui layar kaca, mendayung kayak di sungai-sungainya, menapaki hutan-hutan tropis yang berflora-fauna menakjubkan, juga menyentuh salju abadi Puncak Carstenz Pyramid seperti kawan seorganisasiku di mapala.
Sebagaimana cinta, kadang impian juga bertepuk sebelah tangan. Belum genap seminggu menikmati euforia kegembiraan di Manokwari, aku ditampar sebuah realita yang akan mengubah pikiranku tentang Papua bertahun-tahun ke depan.
Aku adalah perempuan yang lahir dan tumbuh di zona aman. Sekalipun aku menjelajah ke alam liar, aku tidak pernah terancam oleh kehadiran manusia. Pada hari Sabtu, sekitar pukul 07.30 WIT, aku dan seorang kawan baru sesama dosen berolahraga di samping rektorat universitas. Saat asyik berswafoto, tiba-tiba dari belakang kami muncul seorang laki-laki bertubuh pendek gempal dengan wajah beringas. Ia memburu kami diselingi teriakan mengancam. Aku susah payah berusaha lari, sedangkan otak belum sepenuhnya sadar mencerna kejadian.
Di tempat itu, disaksikan kawan yang menjerit-jerit meminta tolong, lelaki itu menjatuhkan dan langsung memukuliku. Aku berusaha bangkit, tapi dia kembali menjatuhkanku, hingga akhirnya ada seorang mahasiswa yang menolong. Lelaki itu kabur dengan sumpah-serapah setelah kalah tenaga.
Aku pulang dengan badan kotor dan rasa sedih yang mengalahkan sakit fisik. Salah apa aku ini? Setelah kejadian itu, akhirnya aku tahu bahwa daerah ini tergolong rawan kejahatan yang disebabkan orang mabuk. Pemabuk berkeliaran di jalan, pasar, emperan toko, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman. Kata orang, gangguan itu sudah biasa terjadi. Jika dilawan, salah-salah malah mendapat logika terbalik: korban menjadi pelaku karena orang mabuk menganiaya tanpa sepenuhnya sadar. Bahkan rekan-rekan saya yang OAP (Orang Asli Papua) pun geram terhadap ulah oknum semacam itu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga.
Tidak lama setelah kejadian itu, aku kembali ditimpa ketakutan lebih besar yang disebabkan isu rasis di Surabaya dan merembet ke Tanah Papua. Manokwari dan kota-kota besar lainnya di Papua chaos kala itu. Pengrusakan bangunan, ancaman verbal, juga ancaman berantai melalui pesan WhatsApp terjadi bertubi-tubi seolah menjadi momentum ledakan kebencian terhadap amber (pendatang). Kampus diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Koneksi internet dibatasi oleh pemerintah. Aku yang saat itu mengungsi ke masjid melewati malam-malam mencekam. Aku kembali bertanya-tanya, salahku apa? Mengapa aku harus turut menanggung dosa orang lain di pulau yang jaraknya ribuan kilometer?
Tidak cukup sampai di situ, bahkan setelah kasus itu mereda pun rumah dinasku tak luput dari gangguan. Ada yang berusaha mencungkil pintu, mencuri jemuran, dan mengintip kamar mandi. Teriring kemarahan dan kekecewaan, sentimen buruk tentang Papua pun menjadi-jadi dalam benak. Aku membungkus semua omong-kosong tentang surga kecil jatuh ke bumi dan melemparkannya entah ke mana. Aku yang sadar diri sebagai amber dan tidak punya seorang pun keluarga di sini lebih baik membatasi gerak seperlunya. Kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan dan dukungan mental dari rekan di kampus, mungkin aku sudah angkat kaki. Setidaknya, aku punya waktu libur 2-3 bulan per tahun untuk menikmati alam bebas di luar Papua.
Sepanjang 2019-2021, seringkali aku iri terhadap pendatang yang tampak senang menelusuri alam Papua, menikmati malam berbintang dan kerlip lampu kota, juga berbaur dalam pelayaran kapal-kapal seolah tidak menyimpan ketakutan. Seorang kawanku, Noviyanti, dosen di kampus itu yang aktif di bidang konservasi laut, pada awal Mei 2022 tiba-tiba menawari perjalanan volunteering konservasi penyu. Ia tahu bahwa aku sempat bermimpi keliling Papua dan pada masa aktif di mapala sedikitnya pernah memperoleh pengalaman konservasi gunung-hutan.
Kegiatan yang ditawarkan Noviyanti akan berlangsung selama 9 hari, mulai 21 Mei 2022 hingga 30 Mei 2022. Aku akan berangkat bersama tiga orang, yaitu Noviyanti, Abigail, dan Aflia. Hal yang terpenting, volunteering ini di bawah tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dari universitas dan keamanan kami terjamin. Pikirku, kesempatan ini seolah nyala yang dihadiahkan Tuhan setelah sekian lama padam. Pelayaran dua hari dua malam di laut lepas Papua, konservasi penyu, dan berinteraksi langsung dengan OAP di kampung terpencil sudah tentu bakal menjadi pengalaman baru bagiku.
Pelayaran Kapal Sabuk Nusantara 112
Ini adalah catatan perjalanan pertamaku di Tanah Papua dengan Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 112 pada 2022 lalu. Aku berangkat dari Pelabuhan Manokwari, Papua Barat, menuju Saubeba di Distrik Manokwari Utara, tepatnya ke Kampung Resye dan Kampung Womom. Perkampungan ini merupakan sebuah wilayah pelosok di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB), Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Program yang kuikuti ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang bergerak di bidang konservasi penyu dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam tulisan ini, aku ingin menceritakan sedikit hal yang tertangkap indera tentang KM Sabuk Nusantara 112 dan dampaknya.
Dilansir dari terupdate.net, KM Sabuk Nusantara 112 dibangun pada 2017 dengan ukuran 1.258 Gross Tonage (GT), panjang (overall length) 60 meter, dan lebar (beam) 15 meter. Kapal yang dioperatori PT PELNI ini melayani pelayaran perintis rute Manokwari-Sorong PP dengan menyinggahi kampung-kampung yang termasuk wilayah terpencil, terdepan, terbelakang, dan perbatasan (3TP), yaitu Saukorem, Wandem, Wau, Warmandi, Saubeba, Kwoor, Hopmare, Werur, Sausapor, dan Mega. Oleh karena itu, durasi pelayarannya pun lebih lama daripada kapal putih PELNI yang biasa menempuh rute Manokwari-Sorong kurang dari 24 jam, seperti halnya KM Gunung Ciremai dan Gunung Dempo.
Dengan tiket seharga Rp20.000, KM Sabuk Nusantara 112 menyediakan fasilitas tempat tidur tingkat, kafetaria, pemutaran film dan musik, serta kamar mandi umum. Rute pelayaran kapal ini ibarat sabuk yang ‘melingkari keliling badan’, menjangkau hampir setiap kampung di rute Manokwari-Sorong.
Saat itu, aku baru menyadari satu hal: karena tidak adanya dermaga di daerah-daerah yang dilaluinya, KM Sabuk Nusantara 112 tidak dapat bersandar. Kapal ini menurunkan jangkar di perairan berkedalaman aman, kemudian perahu-perahu tradisional dari pantai tepi kampung akan datang mengangkut penumpang yang turun dari atau hendak naik ke kapal. Bagiku yang baru kali itu melakukan pelayaran di Papua, aksi mereka tergolong ekstrem. Menyeberangkan manusia dan memindahkan ternak serta segala macam barang dari perahu ke atas kapal di antara hempasan gelombang tentu berisiko.

Sepengamatanku, hampir setiap perahu dari kampung mengangkut berbagai hasil bumi untuk dijual di kota. Pisang mentah, sayuran, daging babi dan rusa, kelapa, pinang, buah sirih, buah-buahan, serta makanan rumahan yang dimasak sendiri. Sebaliknya, masyarakat yang pulang dari kota membawa komoditas untuk keperluan di kampung, seperti perlengkapan rumah tangga, bumbu dapur kemasan, biskuit, mi instan, mentega, aneka tepung, serta minyak tanah dan solar dalam jerigen-jerigen besar.
Pada pelayaran itu, aku mendengar cerita seorang tete (kakek) dari Womom. Menurut ceritanya, dulu belum ada kapal yang menjadi sarana penghubung antarkampung di sepanjang pesisir BLKB. Perjalanan jauh ke kampung maupun kota ditempuh dengan jalan kaki atau mendayung perahu. Ia dan beberapa lelaki Womom pernah berjalan kaki menandu orang sakit selama berhari-hari untuk tiba di Puskesmas terdekat. Maka dari itu, keberadaan KM Sabuk Nusantara 112 dapat mempermudah akses transportasi masyarakat.
Aku melihat kehangatan dalam kesederhanaan orang-orang di tengah hiruk-pikuk bongkar-muat kapal. Ada canda-tawa dan teriakan penuh semangat yang menyambut aktivitas rutin, juga anak-anak dan remaja yang dengan berani berenang di laut dalam tanpa pelampung badan.
Aku kembali teringat pada penggalan lagu “Tanah Papua”. Di sana aku lahir, bersama daun bersama angin aku dibesarkan. Aku mungkin saja takjub pada keberanian anak-anak itu bermain dengan gelombang karena laut bukan tempat bermain masa kanak-kanakku. Bagi mereka, bisa jadi laut adalah kolam alam belakang rumah atau kakak yang mengasuh sekaligus mengajarkan bertahan dan berjuang. Aku terbawa keriangan suasana. Seketika itu, aku lupa pada sentimen negatif soal Papua yang beberapa tahun mengendap di kepala.
Kala itu, aku membayangkan anak-anak itu di masa depan. Mereka akan menempuh pendidikan hingga ke luar negeri seperti generasi Papua masa kini yang wajahnya berseliweran di media sosial memberi motivasi. Mereka dapat mengembangkan potensi perikanan dan kelautan yang melimpah, atau menjadi anggota Basarnas yang pemberani dan berjiwa mulia. Eh, kenapa Basarnas? Iya, aku tiba-tiba teringat pada seorang kawan Basarnas. Menurutnya, di sini sangat kekurangan tenaga rescuer dan minim organisasi potensi Search and Rescue (SAR). Mengenai hal itu, waktu aku tiba di kampus Manokwari pada 2019 silam, aku terkejut karena tidak ada organisasi mapala sebagaimana kampus besar pada umumnya. Padahal, mapala dapat menjadi garda depan potensi SAR daerah. Apalagi, setahuku generasi muda di sini memiliki kelebihan kekuatan fisik dan keberanian.
Di mataku sebagai perantau dari Jawa Barat yang saban hari dimanjakan transportasi serba cepat, berlayar dengan Sabuk Nusantara 112 merupakan wisata eksotis. Aku adalah turis domestik yang terpesona oleh laut biru jernih berbingkai hutan hujan tropis Papua, anak-anak kecil berenang menuju kapal yang baru turun jangkar, daging rusa bumbu rica-rica yang dijajakan perempuan Papua di geladak, anak-anak kampung yang bersukacita tatkala menikmati biskuit di kafetaria, juga jerigen-jerigen besar berisi minyak tanah dan solar.
Iya, saat itu aku seperti seekor katak yang baru keluar dari tempurung dan membuka mata di dunia asing yang sama sekali berbeda.
Seberkas Nyala di Tepian Saubeba
Kami tiba di Resye pada 23 Mei 2022, menjelang tengah hari. Kedatangan kami disertai seruan girang masyarakat kampung yang menyambut datangnya kapal. Seorang mama (ibu) dari kampung langsung menyambut tim kami saat baru saja tiba di pesisir. Ia memberi kami nasihat untuk meletakkan pasir di dahi. Menurut tradisi setempat, hal ini harus dilakukan oleh pendatang baru untuk mencegah penyakit. Kami kemudian berjalan kaki dari pesisir Resye menuju Womom yang memakan waktu sekitar 20 menit.
Resye dan Womom merupakan bagian dari wilayah konservasi, khususya konservasi penyu, di BLKB. Kedua kampung ini bersebelahan dan tergolong kampung kecil. Jumlah penduduknya kurang dari 20 kepala keluarga. Di kampung ini ada satu sekolah dasar dan gereja kecil. Sepanjang menelusuri jalan, tidak ada satu pun rumah yang memperdengarkan musik dan riuh tayangan televisi. Suara-suara yang hadir adalah rupa-rupa kicau burung yang aku tidak tahu namanya, anak-anak yang asyik bermain, dan percakapan penduduk dalam bahasa setempat yang berbaur dengan deburan ombak Pasifik di kejauhan.
Kondisi tanah yang berpasir dan landai menjadikan kampung ini berlimpah kelapa. Dari percakapan sekilas, aku mendengar bahwa sejak dulu masyarakat membuat minyak kelapa, tetapi masih kurang pemasaran. Oleh karena itu, selain konservasi penyu, tim dari LPPM juga telah bertahun-tahun berupaya melakukan pendampingan masyarakat di wilayah konservasi.
Dalam program untuk mendukung ekonomi lokal itu, masyarakat memperoleh pembinaan produksi minyak kelapa yang lebih higienis, mendapat bantuan alat produksi, pengemasan, pendaftaran produk di BPOM, dan memperoleh label halal MUI. Dengan demikian, produk minyak kelapa mereka dapat lebih mendapatkan kepercayaan konsumen sekaligus bisa dipasarkan satu rak dengan produk terkemuka di supermarket.
Pengolahan minyak kelapa ini betul-betul dari hulu ke hilir, mulai dari mencari buah yang layak panen, mengupas tempurung kelapa secara manual, memarutnya, memeras santan, memasaknya hingga menjadi minyak, hingga nanti dibawa ke Manokwari untuk proses labeling dan pemasaran. Mengingat betapa pegal dan sabarnya mereka mengupas tempurung keras kelapa tua, aku tidak akan mengeluh lagi soal harga minyak kelapa homemade yang cenderung lebih mahal daripada minyak sawit kemasan.
Selama empat hari di Resye dan Womom, tim kami juga menyebarkan informasi tentang konservasi penyu melalui film dan permainan. Di kampung ini, film tergolong hiburan langka karena ketersediaan listrik dan bahan bakar yang terbatas. Listrik menyala dari pukul 18.30-24.00 WIT dengan menggunakan genset. Itu pun kalau ada cadangan bahan bakar. Listrik dinyalakan hanya untuk keperluan yang sangat penting bagi hajat orang banyak, seperti mengalirkan air ke rumah-rumah masyarakat.
Bahan bakar minyak tergolong mewah di kampung-kampung tepian Saubeba. Pengadaannya harus dibawa dari ibu kota provinsi Papua Barat, Manokwari, dengan kapal Sabuk Nusantara 112. Sedikitnya, kami membutuhkan waktu dua hari dua malam untuk melayarkan beberapa jerigen bahan bakar demi menyalakan genset dan kompor minyak.
Maka, pada malam 23 Mei 2022, bunyi genset berdengung ke penjuru kampung, memantik semangat tua-muda untuk berkumpul di Rumah Belajar. Tim kami mengundang seluruh penduduk kampung untuk menikmati hiburan sekaligus menyimak sosialisasi pentingnya konservasi penyu yang dikemas dengan permainan dan pembagian hadiah.
Pada momen itu, ada memori masa kecilku yang berkelebat mengajak bernostalgia. Dulu, sebelum tahun 2000, aku pernah bermain masak-masakan dengan kompor Butterfly berbahan bakar minyak tanah. Di dapur Rumah Belajar Kampung Womom ini, aku kembali melihat benda serupa itu. Aku mengisi tanki kecilnya dengan minyak tanah, menyalakan sumbunya hingga keluar api biru, kemudian menggoreng pisang di tengah temaram senter bertenaga baterai.
Sebelum ada kompor minyak tanah masuk di Womom dan Resye, masyarakat setempat memanfaatkan bahan bakar kayu dan daun-daunan kering dari hutan. Kini, di samping menggunakan kompor minyak tanah untuk acara-acara tertentu, kebiasaan memanfaatkan bahan bakar dari hutan masih dilakukan di setiap rumah. Di sini, kayu bakar mudah diperoleh.

Di ruang utama, kulihat masyarakat kampung begitu antusias menikmati rangkaian acara. Terlebih saat menonton film berlatar dan bercerita tentang Papua. Mereka ramai mengomentari jalan cerita dan tertawa bersama jika sang aktor menampilkan kelucuan.
“Adooo… anak kecil Papua sekarang su pintar main film eee! Dong bagus sekali!”
Aduuuh… anak kecil Papua sekarang sudah pintar main film ya! Mereka bagus sekali!
Demikian sedikit celetukan yang paling kuingat terlontar dari seorang perempuan tua yang pandangnya tak lepas dari layar proyektor di dinding kayu. Bagi mereka, film adalah bentuk kebudayaan yang asing karena sulit dijangkau. Jangankan mengakses tontonan, jaringan internet pun kadang hanya dapat ditangkap di titik-titik yang tidak menentu. Tonny Duwiri (Todu), seorang anggota tim yang sudah tinggal setahun di sana, bercerita bahwa ia dan pemuda setempat baru dapat mencari kabar tentang dunia luar ketika kapal putih PELNI melintas. Mereka berlari demi mengejar sinyal internet yang dipancarkan kapal PELNI hingga tak sadar telah menempuh garis pantai berkilo-kilo meter jauhnya.
Pun demikian dengan biskuit, jajanan anak-anak, dan cita rasa makanan khas supermarket. Bagi sebagian warga kampung, makanan kemasan ibarat wisata rasa dan selalu dinantikan jika kapal tiba. Bagiku yang saban hari bergaul dengan jajanan kota, clean eating yang diterapkan masyarakat kampung justru menjadi sajian luar biasa. Terlepas dari polemik kandungan gizi dan isu kesehatan dalam makanan kemasan, sesuatu yang jarang didapat biasanya terasa istimewa. Mereka kudengar berbincang santai perihal hidangan di sela-sela menonton film. Pisang goreng, singkong dan keladi kukus, sungguh lezat dinikmati bersama kopi atau teh dengan tambahan sedikit gula.
Biasanya, cenderamata sosialisasi di kota berwujud kaos, buku catatan, payung, atau tumbler bertuliskan slogan-slogan dan logo. Di kampung ini, mereka lebih mengharapkan bahan pangan yang jarang diperoleh, seperti bawang, garam, gula pasir, teh, kopi, dan aneka biskuit.
Kedatangan tim dari ibu kota provinsi mungkin saja membawa angin segar bagi anak-anak di kampung itu. Mereka tampak senang mendatangi Rumah Belajar di Womom maupun Resye untuk membaca buku-buku anak yang penuh warna, juga mengoperasikan satu-satunya komputer di wilayah itu. Namun, komputer itu tidak saban hari menyala karena keterbatasan energi. Komputer hanya dapat dioperasikan jika tersedia solar yang cukup dan guru yang mendampingi mereka.
Menurut penuturan masyarakat setempat, dulu pekerjaan utama mereka adalah nelayan, berburu, menganyam noken, dan bertani. Setelah ada Sabuk Nusantara 112, mata pencaharian mereka bertambah dengan memproduksi minyak kelapa dan menjualnya ke kota, berdagang hasil bumi di kapal maupun kota terdekat, dan ada pula yang membuka kios kelontong kecil-kecilan.
Konservasi Penyu di Pantai Wembrak

BLKB Papua, yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, sangat penting untuk konservasi di tingkat nasional dan internasional. Wilayah ini memiliki sumber daya hayati laut yang sangat kaya. Di lokasi ini, kita dapat menemukan lebih dari 600 spesies karang yang merupakan 75% dari spesies karang keras di seluruh dunia. Selain itu, wilayah ini adalah rumah bagi lebih dari 1700 spesies ikan karang, serta habitat bagi berbagai jenis mamalia laut yang terancam punah, seperti penyu. Salah satu wilayah konservasi penyu ini adalah Pantai Wembrak yang letaknya segaris dengan Womom dan Resye.
Sebenarnya, kampung tepi pantai di wilayah Papua sudah banyak yang dari dulu menerapkan konservasi tradisional secara turun-temurun. Hal ini dikenal dengan istilah sasi atau mengkarantina dan menerapkan pelarangan pengambilan biota laut dalam jangka waktu tertentu serta membatasi pengambilan. Misal untuk mengambil ikan, masyarakat adat melarang penggunaan jaring besar, racun buatan, dan peledak karena mereka sadar bahwa tindakan itu akan mempercepat kepunahan biota laut. Pada umumnya, mereka menangkap ikan dengan cara memancing dan memasang jebakan-jebakan tradisional seperti rakkang (jebakan kepiting) dan bubu (jebakan ikan dari anyaman bambu).
Maka, kehadiran konservasi modern ibarat perpanjangan tangan untuk pelestarian sekaligus pemanenan hasil laut yang berkelanjutan, terkontrol, dan terjamin secara hukum. Konservasi ini pun merupakan sebuah upaya mempertemukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern tentang kelautan dan diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Setelah dua hari tinggal di Womom, aku diajak berlayar oleh seorang tenaga ahli konservasi dari tim kami yang telah setahun di wilayah ini memantau peneluran penyu. Ia adalah Kakak Todu, putra asli Papua yang hobi berkelana. Sejak pertemuan yang hanya sekejap itu, kami rupanya sama-sama merasa saling cocok karena sehobi. Makanya ia langsung mengajakku. Aku tanpa ragu menyambut tawarannya dengan mantap.
Sungguh tepat waktu! Saat aku tiba di Wembrak, masa puncak peneluran penyu telah tiba. Untuk mencapai Pos Wembrak, kita dapat trekking selama satu jam atau naik perahu. Untuk mempersingkat waktu, kami memilih naik perahu. Sepanjang siang itu, gelombangnya cukup besar sehingga pelayarannya seperti arung jeram dan bermandikan air garam.
Suasana di Pos Wembrak cukup ramai karena ada pembangunan toilet baru di belakang posko. Di sana, aku bertemu dua orang teman baru, Fany dan Ika. Kami langsung berinteraksi akrab dalam waktu singkat. Memasak bersama, berbicara tentang berbagai topik, dan tidur dalam satu ruangan di posko. Agas atau nyamuk pantai di sana ganas luar biasa. Pantas saja kedua perempuan itu membangun tenda di dalam ruangan. Sebagai manusia segala medan, Kakak Todu dapat tidur di mana saja dan kelihatannya sudah kebal gigitan nyamuk.
Seperti yang diinstruksikan Kakak Todu siang harinya, kami melakukan patroli penyu lewat tengah malam. Karena kaki Ika sakit, hanya Kakak Todu dan aku yang patroli malam itu. Selain berpatroli, kami juga harus menjaga sarang penyu dan mendatanya. Cara kerja patroli pada malam itu, patroler berjalan ke titik yang telah ditentukan sejauh kurang lebih dua jam bolak-balik jalan kaki. Tim pertama dan kedua masing-masing memegang senter bercahaya merah dan putih sebagai kode komunikasi mengenai pergerakan penyu: naik ke pantai, turun, bersarang, atau tidak jadi bertelur. Malam pertama di Wembrak, tidak ada penyu yang bertelur. Ada satu penyu belimbing yang naik, tapi turun lagi. Barulah pada malam kedua, kami (aku , Kakak Todu, Fany, dan Ika) menyaksikan penyu belimbing sukses bertelur.
Penyu yang naik ke pantai belum tentu mau bertelur saat pertama kali naik. Ada kalanya penyu hanya mengecek lokasi kemudian turun lagi. Penyu juga sensitif terhadap gangguan dari cahaya putih, terutama sebelum mengeluarkan telur dan menguburnya. Jadi, kami menggunakan senter bercahaya merah sepanjang patroli dan menunggui penyu bertelur. Setelah penyu berhasil mengubur telurnya, kami boleh menyalakan senter cahaya putih. Itu pun tidak sembarangan, hanya satub sumber cahaya untuk keperluan pendataan dan pengukuran. Umumnya, penyu terinsting mengikuti sinar cahaya putih sehingga jika dinyalakan beramai-ramai akan membuatnya bingung dan terganggu.
Saat menunggu penyu bertelur pun kami tidak boleh berisik dan harus menjaga jarak. Selain memberi privasi, penyu bisa agresif. Tenaganya besar dan berisiko membahayakan. Bahkan, kata Kakak Todu, sirip penyu dapat mematahkan dahan cukup besar jika merasa terganggu.
Di wilayah ini, penyu biasa bertelur pada musim teduh (ombak relatif kecil). Biasanya, penyu naik ke pesisir dari malam hingga menjelang pagi. Para patroler penyu umumnya menelusuri pantai mulai pukul 20.00 WIT. Patroler biasanya terdiri dari dua tim kecil dengan personel masing-masing satu sampai tiga orang.
Induk penyu yang telah berhasil bertelur akan langsung mengubur telurnya dengan pasir, kemudian kembali ke laut tanpa menunggu menetas. Proses selanjutnya benar-benar diserahkan kepada siklus alam. Spesies penyu belimbing dapat bertelur hingga 200 butir. Namun, yang berhasil selamat menjadi tukik (anak penyu) dapat kurang dari 50%. Saya terharu melihat proses ini. Tukik sekecil itu merangkak dari timbunan pasir setelah keluar cangkang, kemudian merayap dengan sirip mungilnya yang gemetar, mengikuti deburan ombak dan aroma laut yang secara alamiah tertanam dalam instingnya. Mereka berenang-renang di Pasifik yang luas dan dalam, juga berjuang bertahan hidup dari segala bahaya yang mengintai dari berbagai arah.
Telur penyu punya predator alamiah, yaitu babi hutan dan rusa. Oleh karena itu, setelah induk penyu selesai bertelur, tim konservasi membuat perlindungan sarang dengan ranting dan daun yang kokoh. Mereka dan penduduk setempat juga ada kalanya berburu babi hutan dan rusa yang sangat melimpah di hutan pantai untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Cara berburunya pun sederhana, hanya menggunakan tombak dan dibantu seekor anjing. Perburuan dilarang menggunakan senjata. Mereka mengambil secukupnya.

Sebelum ada upaya konservasi, telur dan daging penyu di wilayah itu kerap dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Karapas (cangkang) pun digunakan sebagai bahan kerajinan tangan dan cukup mahal. Kini masyarakat telah teredukasi dengan baik bahwa penyu termasuk hewan langka yang harus dilindungi. Selain penyu, di sini pun merupakan habitat asli hewan-hewan endemik seperti lau-lau (kanguru Papua) dan mambruk (burung dara mahkota). Tim konservasi dan masyarakat bahu-membahu menjaga kelestariannya.
Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan singkat itu. Di antaranya adalah bersyukur pada apapun yang dikaruniakan Tuhan, serta bersikap santun dan bijak pada alam. Berkesempatan menyaksikan penyu bertelur, bagi saya adalah kesempatan menyaksikan suatu kebesaran Tuhan. Keberadaannya hadir sebagai keselarasan alam.
Keberadaan program konservasi di BLKB diharapkan dapat menjadi matahari terbit yang hadirnya sebagai harapan bagi kelestarian penyu di tengah besarnya ancaman. Kegigihannya dalam upaya konservasi, serta berupaya merangkul masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan, menjadi sinergi positif yang harus terus menyala. Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan transportasi yang menghubungkan kota dengan wilayah-wilayah di sepanjang BLKB. Melalui eksistensi dan pelayanan Sabuk Nusantara 112 inilah sinergi dapat terwujud di BLKB dengan lebih efisien, juga memperdekat jarak transfer ilmu pengetahuan dan geliat ekonomi masyarakat.
Pengalaman ini pun bagiku merupakan bahan renungan untuk diri sendiri, sekaligus juga berharap dapat menjadi refleksi bersama tentang tantangan hidup di pelosok negeri. Ya, itu adalah kesanku ketika mendapat pengalaman dan visual baru di tempat yang juga baru. Bisa jadi banyak bagian yang mungkin digambarkan tidak utuh, berkesan bias, dan mengundang banyak tanya. Aku tidak cukup waktu untuk menangkap keseluruhan konteks dan fakta yang mengakar di sana. Kisah perjalanan ini hanya sepenggal catatan pertemuan sekilas antara dua sisi yang memiliki konteks dan latar belakang berbeda. Bagiku, selama berlayar ke Saubeba, kesulitan mendapat listrik dan internet merupakan tantangan besar. Di kota tempatku lahir dan bertumbuh, aku tidak sulit mengakses transportasi dan sumber energi. Sementara itu, di Saubeba aku tidak mendengar mereka mengeluh karena listrik belum menyala atau kapal yang belum tiba. Hal yang kukenang justru ungkapan syukur seorang lelaki tua Papua bahwa Tuhan telah memberikan kemurahan-Nya lewat Sabuk Nusantara 112 dan ia berbahagia menjadi bagian dari tanah itu.
“Ini sa pu tanah. Sa pu leluhur ada di sini. Sa tra akan ke mana-mana.”
Ini tanahku. Leluhurku ada di sini. Saya tidak akan ke mana-mana.
Berlandaskan ucapan itu, mungkin saja mereka memang merasa tidak kesulitan hanya karena susah internet dan listrik. Toh mereka punya pola hidup yang berbeda dariku. Hadirnya kapal Sabuk Nusantara 112 yang menurutku butuh kesabaran karena menghabiskan waktu dua hari dua malam menuju kota bisa jadi menurut mereka sudah lebih dari cukup. Orang yang terbiasa dimanjakan kecepatan pesawat, kereta api, internet, dan listrik sepertiku tentu sulit menerjemahkan kehidupan di Papua. Bahkan, aku tidak mampu menerka apa arti sebenarnya dari binar mata anak-anak Resye dan Womom ketika komputer dinyalakan, seruan dan tepuk tangan meriah mama-mama saat menonton adegan film, dan senyuman ketika tim kami berlabuh.
Mungkin saja seberkas nyala itu bukan andilku di tengah mereka, melainkan energi kebaikan mereka yang memantik nyala padaku. Nyala yang seketika itu menerangi benak gelap yang diselimuti sentimen negatif. Aku tarik kembali ucapan buruk 2019 silam. Surga kecil yang jatuh ke bumi di Tanah Papua bukan omong-kosong. Seusai perjalanan itu, aku kembali menempuh kepingan-kepingan surga di sisi lain Papua untuk belajar adil sejak dalam pikiran.
Editor: Ragil Cahya Maulana