Pseudo-Entertainment #1, Apa yang Tersisa dari Masa Depan
Sepanjang kurang lebih satu bulan, sejak Februari-Maret 2025, sembilan seniman, penulis, aktivis dan satu kolektif seni menjadi partisipan program residensi penelitian artistik Pseudo-Entertainment #1, Apa yang Tersisa dari Masa Depan. Program tersebut diinisiasi oleh Bandung Performing Art Forum (Yayasan Seni Pertunjukan Bandung). Kesepuluh partisipan program ini antara lain, Adhea Rizky Febrian (Aktivis, Bandung), Amina Gaylene (Penulis, Depok), Arif Furqan (Seniman, Yogyakarta), Arum Dayu (Seniman, Bandung), Ganda Swarna (Aktor, Ciputat), Fachry Matlawa (Penari/Koreografer, Papua), Mega Buana (Penari/Koreografer, Bandung), Rama Anggara (Komponis, Pontianak), Syamsul Arifin (Aktor, Samapang) serta Angela Sunaryo (Bandung) dan Helmi Hardian (Surabaya) dari kolektif Bioahaha.
Pseudo-Entertainment digagas sebagai sebuah lingkungan penelitian artistik yang mengundang seniman, penulis, peneliti, serta warga dari berbagai latar belakang bidang kerja dan keahlian untuk menginvestigasi kembali hubungan-hubungan antara seniman, karya seni, warga penonton, dan konteks sosial politik yang melingkupinya. Investigasi dilakukan dengan membangun proses interaksi dan pertukaran yang intens antar seniman, seniman dengan warga dan seluruh ekosistem termasuk di dalamnya entitas biologis dan non biologis yang membentuk hidup bersama.
Para partisipan didorong untuk mempertanyakan sekaligus membayangkan kembali motif, gagasan, praktik, bentuk, dan kepenontonan seni secara radikal sebagai upaya membentang dinamika dorongan kreativitas, gairah kesenangan, kapitalisme afektif, dan cita-cita tentang transformasi sosial yang turut membangun medan produksi seni. Pseudo-Entertainment dirangkai dalam program lokakarya, riset mandiri, residensi, dan penciptaan karya bersama dalam format pertunjukan berdurasi panjang (long duration performance).
Pseudo-Entertainment #1 – Apa yang Tersisa dari Masa Depan dikuratori oleh Eka Putra Nggalu bersama dengan dua fasilitator yaitu Arsita Iswardani dan Josh Marcy, dengan Taufik Darwis sebagai direktur artistik.
Seluruh kerangka proyek Pseudo-Entertainment menempatkan Bandung sebagai ruang (space) dan gagasan (idea). Sebagai ruang, Bandung adalah medan pascakolonial yang dinamis. Ia adalah juga lanskap-lanskap ingatan (memoryscapes) yang menyimpan luka-luka sejarah (wounded space). Sebagai gagasan, ia mewarisi marwah dan legasi Konferensi Asia Afrika, sebuah gestur dekolonial ketika negara-negara pascakolonial berupaya menentukan pilihan politiknya sendiri (delinking), yang kelak dibaca sebagai upaya memutus epistemologi kolonial-modern-kapitalistik. Bandung juga disikapi sebagai cermin untuk merefleksikan seluruh pembangunan hari ini.
Para partisipan penelitian berhadapan dengan Bandung hari ini sebagai sebuah situs urban yang secara dominan bergerak dengan logika pembangunan-kapitalistik. Ia membentangkan komodifikasi dan spektakularisasi, gairah untuk terus selalu menghasilkan dan menghabiskan, hasrat untuk selalu menjadi prestisius dan menguasai di satu sisi, dan menyisakan dampak sosial seperti perampasan lahan, kemiskinan struktural, buruh, turisme eksploitatif, ekologi, politik identitas, dll., di sisi yang lain. Isu agraria, termasuk di dalamnya perampasan lahan atas nama pembangunan yang berkelindan dengan perusakan ekologi adalah salah satu yang paling marak terjadi di Indonesia hari-hari ini.
Inkubasi Kolektif dan Penciptaan Kartografi Sosial
Program residensi di Bandung berlangsung selama kurang lebih empat minggu, sejak 10 Februari hingga 10 Maret 2025. Selama residensi, para partisipan melakukan beberapa kegiatan antara lain kunjungan kelompok ke beberapa tempat seperti Dago Elos, Braga, landmark Asia-Afrika, komunitas difabel Dilans, dan beberapa ruang seni budaya di seputaran kota Bandung. Selain kunjungan kelompok, para partisipan juga melakukan riset-riset mandiri di situs-situs yang tertarik untuk ditelusuri masing-masing. Ada yang melakukan riset di Dago Elos yang sedang berjuang dengan isu penggusuran, di pasar Sarijadi yang megah tetapi sepi pengunjung, di sungai Cikapundung yang perlahan diabaikan, di rusunawa Rancacili dan di beberapa tempat lainnya.
Riset-riset sosial yang dilakukan oleh para partisipan juga dibarengi dengan workshop-workshop, majelis ide, klinik dan laboratorium karya sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman, pengayaan, ujicoba dan pematangan karya. Forum-forum ini menjadi sangat menarik karena para partisipan berasal dari ragam latar belakang disiplin, konteks sosial budaya, dan gender. Hal ini membuka ruang pertukaran praktik artistik dan refleksi bersama tentang perubahan ruang juga relasi sosial serta menciptakan narasi yang inklusif. Proses yang berlangsung sungguh membangun kesepahaman, solidaritas, dan sikap saling berbagi dalam semangat kolektif.
Setelah tiga minggu melakukan penelitian, para partisipan kemudian mengadakan presentasi karya-karya artistik. Proses presentasi berlangsung selama tiga hari dari tanggal 7-9 Maret 2025, di beberapa situs di kota Bandung, seperti Gelanggang Olah Rasa, Dago Elos, landmark Asia-Afrika,
Karya-karya yang dihasilkan dari residensi penelitian artistik ini sungguh kaya dan beragam. Para partisipan seperti sedang membangun kartografi sosial kota, lewat identifikasi isu, modal, dan potensi, penglihatan yang mendetail dan amatan menyeluruh, penggalian cerita dan perumusan wacana.
Kartografi sosial kota disajikan dalam pertanyaan-pertanyaan gugatan, refleksi kritis, pernyataan perlawanan, hingga ironi-ironi paradoksal.
Spektrum kartografi sosial yang luas tersebut disajikan dalam keragaman artistik: permainan, tur sensorik, pertunjukan tari, instalasi audio, pseudo workshop, dan laboratorium terbuka. Ekspresi-ekspresi artistik tersebut menyoal ragam tema: sejarah kolonial, developmentalisme kapitalistik, kerentanan komunal, ekologi, perawatan radikal, hingga perlawanan warga.
Karya-karya Pseudo-Entertainment #1: Dari Radical Caring hingga Panopticon
Beberapa karya yang bisa ditunjuk misalnya karya Mega Buana yang menekankan prinsip radical caring, sebuah laku perawatan yang sepenuhnya berusaha disadari, diniatkan, dan diupayakan dalam membangun relasi konsensual interpersonal. Radical caring dibangun atas dasar kesadaran akan dinamika potensi dan limitasi tubuh, rasa saling percaya, sikap saling menghormati, serta keterbukaan berbagi serta penyerahan diri yang total antar personal.
Karya tari yang berangkat dari eksplorasi atas tali dalam praktik shibari/kinbaku (rope) ini beririsan secara gagasan dengan karya fotografi Adhea Rizky Febrian yang bicara soal kasih sayang sebagai spirit yang terus membakar semangat perjuangan warga Dago Elos. Jika belakangan potret yang tersebar di media mengenai Dago Elos adalah potret-potret perjuangan dengan tangan terkepal, karya Adhea ingin merekam kenangan-kenangan warga yang lebih personal: tentang rumah, tentang keluarga, tentang kasih sayang yang terus menggerakkan denyut nadi dan menjaga bara api semangat warga Dago Elos tak lekang padam.
Arum Dayu dan Syamsul Arifin juga turut merekam narasi warga Dago Elos. Jika Arum menggunakan musik dengan memanfaatkan artificial intelligence sebagai moda kerja untuk menciptakan lagu yang merekam semangat perjuangan warga Dago Elos, Syamsul sebaliknya memilih memantulkan seluruh narasi Dago Elos pada pengalamannya sebagai seorang nelayan dari Sampang yang rentan berhadapan dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah. Syamsul ingin belajar dari warga Dago Elos perihal resistensi dan solidaritas.
Dalam kasus yang lain, Ganda Swarna juga memotret kerentanan warga lewat lanskap suara (soundscape) yang diambil dari tiga situs yang mengalami tegangan penggusuran-pembangunan, yaitu Kiara Arta Park, rusunawa Rancacili, dan Dago Elos. Lanskap suara yang direkam kemudian kodefikasi dan dikomposisi menjadi playlist yang diarahkan untuk didengarkan lewat laku tubuh di waktu luang dengan niat memberi jeda refleksi bagi tubuh-tubuh yang rasa-rasanya selalu dituntut untuk aktif bekerja: bahwa di balik seluruh logika pembangunan kapitalis-neoliberal ini, kita adalah yang rentan, yang siap digusur kapan saja.
Dengan pendekatan artistik yang hampir sama melalui soundscape, Rama Anggara menyoal bagaimana logika tata kota di Bandung justru mengabaikan sungai sebagai referensi material dari seluruh tradisi, nilai, dan rasa-merasa orang Sunda. Disajikan dalam bentuk pertunjukan dan instalasi audio spasial quadraphonic, Rama berupaya menghadirkan pengalaman mendengarkan audio imersif yang merefleksikan varian gemericik aliran sungai dan alam sekitarnya, mengajak audiens merasakan perjalanan, gejala perubahan, hingga kedalaman hubungan masyarakat dengan lingkungannya.
Persoalan spektakularisasi pembangunan kota juga dilihat oleh Amina Gaylene. Proyek-proyek estetisasi kota sering kali tidak menimbang realitas sosial dan fungsional: bagaimana warga benar-benar menggunakan dan mengalami ruang yang dipercantik.
Amina melihat ada intensi dan upaya menyusupkan gagasan estetis dan artistik tertentu pada banyak kasus pembangunan di Bandung. Ia menyebutnya dengan puitika kota. Sementara, di satu sisi, ada situs seperti pasar Sarijadi yang dibangun dengan orientasi artistik yang sangat megah tetapi tak fungsional.
Amina kemudian membuat workshop puisi bermodal kalimat dan frasa temuan dari risetnya di Pasar Sarijadi. Workshop puisi ini bermain-main dengan ironi puitika kota, sembari pada saat yang bersamaan mendeteksi paradigma puitika macam ada yang cenderung bersemayam di kepala para partisipan workshop yang berasal dari skena sastra di Bandung.
Format workshop/laboratorium terbuka juga dipakai oleh Biohaha dalam menjalankan karya mereka. Karya mereka berbentuk riset partisipatoris berbasis navigasi multisensori yang mengeksplorasi pengalaman-pengalaman ketubuhan (inderawi) dalam memahami kota. Karya ini mengajak peserta menjelajahi Braga melalui sensewalking. Interaksi inderawi—penglihatan, suara, sentuhan, bau, dan rasa— dicatat sebagai data dengan pola pencatatan tertentu, selanjutnya diterjemahkan menjadi partitur generatif. Partitur ini kemudian dipresentasikan dalam bentuk pertunjukan kolektif, menghadirkan alih wahana dari data ke suara yang menggambarkan lintas pengalaman sensorium mengenai Braga.
Tur atau berjalan sebagai modus juga dipakai oleh Arif Furqan dalam karyanya. Bedanya Arif Furqan menciptakan game sebagai navigator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait sejarah. Sebagaimana praktik-praktiknya sebelumnya, ia memainkan tegangan-tegangan antara cerita personal, memori kolektif dan historiografi. Kali ini, Arif Furqon bermain-main dengan sejarah di landmark Asia-Afrika, mengajak penonton untuk menjawab secara kritis polemik-polemik di sekitar sejara Indonesia yang terpampang di sepanjang jalan yang dibangun Daendels.
Jika Arif Furqan ingin mendorong narasi pascakolonial muncul ke permukaan, Fachry Matlawa mempertegasnya dengan memunculkan gagasan tentang ‘panopticon’ dan tatapan-tatapan yang mengkotak-kotakan manusia dalam kategori-kategori yang menunggal. Ia mengelola rekaman CCTV di beberapa sudut kota Bandung sebagai mata kamera yang merekam gerak tarinya. Bagi Fachry Matlawa, mata kamera tersebut ia pandang sebagai panopticon yang selalu mengawasi dan menyelidiki gerak laku individu sebagai bagian dari proses pendisiplinan. Sebagai keturunan Sulawesi yang lahir dan besar di Papua, Fachry menyadari bahwa tubuhnya yang bergerak dan menari di Bandung, Jawa, serta Indonesia bisa jadi adalah antitesis yang menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi, kontrol, dan politik representasi dengan cara-cara kultural.
Estetika (dalam) Jaringan: Berpijak pada The Not Yet
Secara sekilas, karya-karya yang dipresentasikan dalam penelitian artistik Pseudo-Entertainment #1 seolah berdiri sendiri-sendiri sebagai karya singular. Sebenarnya, karya-karya itu adalah bentuk-bentuk modular yang ditetaskan dari proses inkubasi bersama, mulai dari tataran penajaman gagasan riset hingga bagaimana riset tersebut dilakukan dan dipresentasikan. Ujicoba-ujicoba yang dilakukan sepanjang riset pun dibentang serta dibuka dalam kerja maupun percakapan bersama.
Perspektif penciptaan bersama (collective creation) Teater Garasi cukup banyak digunakan dengan penandaan yang tak ketat pada tahapan-tahapan proses, mulai dari merumuskan pertanyaan (locating the question) hingga presentasi (presentation). Sebagai metodologi, penciptaan bersama menekankan pada kemandirian para partisipan sebagai kreator dalam menemukan dan mempertajam gagasan karyanya yang disarikan dari kata-kata kunci awal yang dikumpulkan dalam proses menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci kuratorial, sesederhana bagaimana para partisipan melihat Bandung dan persoalannya hari ini dari sudut pandang praktik maupun konteks sosial budayanya masing-masing?
Metodologi penciptaan bersama yang dalam praktiknya pada tiap-tiap tahapan bisa dibedah lebih rinci dengan pertanyaan-pertanyaan 5W1H juga memberi wawasan yang operasional bagi proses riset dan pencarian bahasa atau bentuk yang paling relevan untuk menghadirkan seluruh gagasan yang ditawarkan agar dapat dikaji lebih jauh, baik oleh kreator maupun fasilitator dan kurator.
Niatan Pseudo-Entertainment membangun lingkungan penelitian kolektif yang reparatif boleh dibilang berhasil diwujudkan dengan seluruh proses yang dinamis dan memberikan ruang bagi karya maupun seniman untuk terus bertumbuh, gagal, dan bertumbuh lagi dalam proses yang sirkular serta bertaut satu sama lain.Tentu dinamika masing-masing karya modular bervariasi, tetapi bahwa dalam kerangka waktu programatik yang tertentu, proses dialog kritis, refleksi antar peserta, interaksi lintas praktik juga disiplin sungguh berkontribusi dalam membangun kedalaman dan penguatan riset serta laboratorium kolektif.
Kedalaman dan penguatan riset dan laboratorium kolektif ini memungkinkan yang pertama, karya-karya modular ini terhubung dalam prinsip-prinsip utama yang mendasari seluruh penelitian, penciptaan, maupun ekspresi artistik. Prinsip-prinsip itu -tentu sudah banyak kali disebut- antara lain berakar pada pembacaan yang kritis atas konteks, kesediaan mendengarkan dengan penuh empati (radical listening), berpikir reparatif (reparative thinking) dan seluruh kerangka penciptaan bersama itu sendiri.
Yang kedua, karya-karya yang juga berangkat dari penciptaan bersama kartografi sosial kota dengan segera ‘mengungkapkan’ atau ‘menarik keluar’ elemen-elemen yang tersembunyi dari pengalaman sosial masing-masing seniman, terutama dalam interaksi para seniman dengan komunitas-komunitas maupun orang-orang yang ditemui sepanjang residensi. Dengan demikian, sepuluh karya yang dipresentasikan dalam Pseudo-Entertainment kali ini adalah juga sebuah dokumentasi sosial, sebuah dokumen pengetahuan, serentak kartografi isu, modal, dan potensi lintas konteks dan batas yang amat berharga.
Semuanya berjalin dalam spektrum yang ketika dibentang, terhampar kait kelindan yang menampakkan kenyataan keberagaman dan perlintasan yang kaya serta potensial sebab amat mungkin bertaut satu sama lain maupun membuka jalannya masing-masing dengan satu laboratorium terbayang bersama seluruh kartografi kolektif yang telah dibangun selama proses residensi.
Penekanan pada potensi tidak secara permisif menempatkan karya-karya yang dipresentasikan pada ‘status work in progress’ tetapi lebih dari pada itu menajamkan gagasan not yet sebagai sebuah paradigma berpikir dan merasa. Seluruh proses penelitian hingga presentasi menempatkan seluruh unsur dalam karya dalam proses ‘menjadi’, meletakkannya sebagai potensi yang selalu punya peluang bertumbuh dalam horison tak terbatas.
Potensi ini dengan demikian tak hanya mengenai yang terkandung dalam karya maupun seniman-senimannya diri, tetapi juga dalam seluruh karakter partisipatif dalam seluruh proses hingga keterbukaan untuk bertumbuh bersama publik penonton, dan kenyataan sosial budaya yang lebih luas. Dalam konteks jangka panjang, pertumbuhan ini juga bisa dibayangkan berlangsung di luar skema programatik, dalam interaksi dan pertemuan dengan konteks-konteks yang lain pun lebih beragam.
Dalam kerangka not yet ini, proses yang regeneratif berlangsung dalam kolektivitas dan konektivitas yang paling mewujud. Proses yang regeneratif ini tidak dibayangkan dalam model pertumbuhan tanpa batas, tetapi melalui reaktualisasi yang memungkinkan proyek bertransformasi seiring temuan baru, pemikiran artistik, dan respons terhadap tantangan sosial-politik yang terus berubah.
Karya-karya yang lahir dari inkubasi Pseudo-Entertainment didorong untuk menemukan jalannya sendiri-sendiri, menyebarkan nilai-nilai dan benih-benih gagasan yang diusungnya secara rimpang, dan terhubung dalam satu jejak penelusuran estetika yang menolak tunduk pada prinsip-prinsip linearitas-progresif tetapi selalu terbuka pada spektrum serta proses analectica yang memungkinkan berlangsungnya percakapan lintas batas.
Dengan segala kenyataan produksinya, Pseudo-Entertainment masih punya pekerjaan rumah yang berat dalam mengidentifikasi ulang publiknya. Bahwa penciptaan yang sosial (the social) berlangsung di kalangan partisipan tidak serta merta menunjukkan bahwa masing-masing karya telah menemukan publik yang beragam dan menawarkan spekulasi yang relevan dan kontekstual. Waktu yang dihabiskan dalam proses penciptaan, kenyataan produksi dan logistik yang dinamis tak memungkinkan tim kreatif punya kemewahan waktu untuk memikirkan proyeksi serta pengembangan audiens. Sementara, penciptaan yang sosial, sebenarnya adalah juga perihal proses pertemuan dan percakapan dengan audiens serta seluruh upaya menyemai pengetahuan serta nilai-nilai yang telah ditumbuhkembangkan dalam seluruh proses inkubasi. Karena hanya dengan cara demikian, benih-benih imajinasi tentang masa depan yang lebih baik (speculative intervention) yang ditawarkan oleh tiap-tiap karya, menemukan ladangnya yang paling potensial.

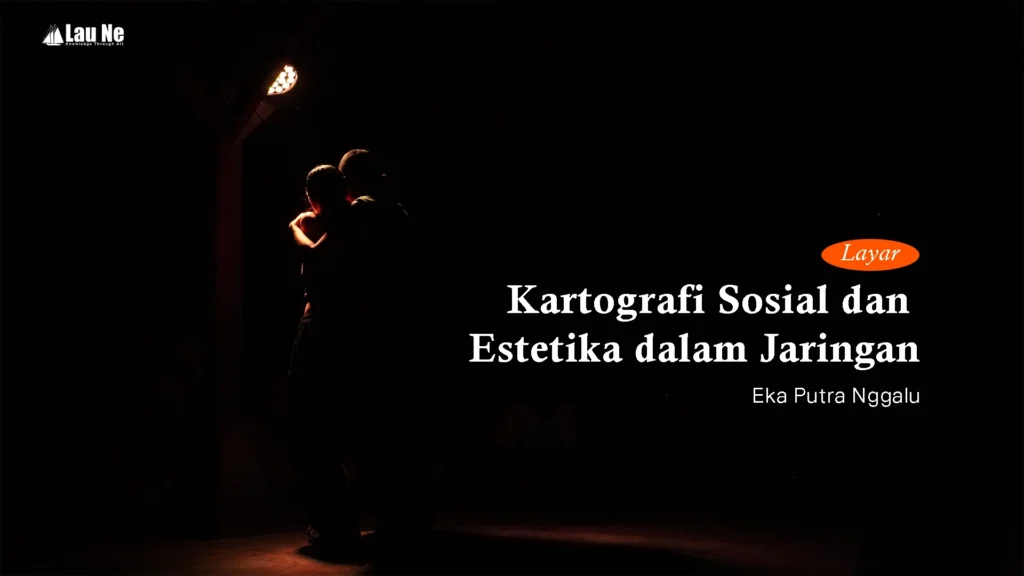



2 Responses
Menyala sekali tulisan ini….sehat selalu para seniman Indonesia…menyala betul metodologi Penciptaan Garasi saya ingin baca bukunya juga