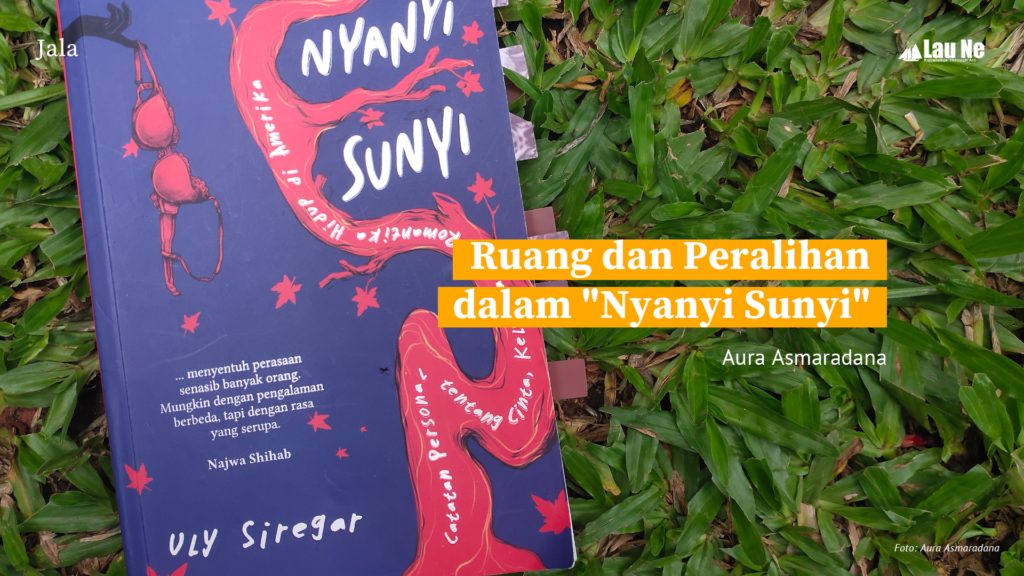Resensi buku ini dibawakan pada Kajian Jumaahan #14, “Menghikmati Nyanyi Sunyi Uly Siregar” Jumat, 5 Mei 2023 di Kedai Jante Perpustakaan Ajip Rosidi Jalan Garut No. 2 Bandung.
Judul buku: Nyanyi Sunyi, Catatan Personal tentang Cinta, Keluarga, dan Romantika Hidup di Amerika
Pengarang: Uly Siregar
Penerbit: Cantrik Pustaka
Cetakan dan tahun terbit: Cetakan 1, Februari 2023
Ketebalan: 168 hlm
ISBN: 978-623-6063-94-1
Buku dengan sampul nuansa biru merah bergambar dedaunan maple gugur serta bra melambai itu saya baca berurutan dari awal hingga akhir. Namun kalau punya kesempatan untuk membacanya ulang, saya tahu bahwa buku ini bisa mulai dibaca dari judul di bagian tengah, atau bahkan dari bagian epilog yang ditulis oleh Agnes Nauli S.W Sianipar. Meskipun esai-esai dalam buku ini dibaca secara acak, menurut saya, tidak akan banyak berpengaruh pada soliditas kontennya.
Nyanyi Sunyi, Catatan Personal tentang Cinta, Keluarga, dan Romantika Hidup di Amerika adalah buku kumpulan esai personal Uly Siregar. Sesuai judulnya, penulis membahas tentang kehidupan sejak lahir hingga selesai sekolah di Palembang, sekolah tinggi di Bandung, berkarier di Jakarta, hingga kehidupannya di Amerika Serikat, serta peralihan di antaranya. Dalam kumpulan esai ini, pembaca akan menemukan hal paling personal hingga paling politis dari sudut pandang yang intim.
Meski banyak hal dibahas penulis dalam buku ini, salah satu hal yang saya tangkap paling dulu adalah cara penulis menyajikan citra ruang-ruang dalam hidupnya, peralihan dari satu ruang ke ruang lain, serta pemaknaannya terhadap hal-hal yang ditinggalkan atau dibawa serta. Kisah-kisah peralihan yang disajikan buku ini menggambarkan keterikatan manusia pada ruang di sekitarnya, dan mungkin secara subjektif bisa menjawab: mengapa keterikatan itu bisa terjadi?

Ruang fisik, ruang mental
Auguste Comte menyatakan bahwa keseimbangan mental, pertama-tama disebabkan oleh fakta bahwa objek fisik yang berkontak dengan seseorang di kehidupan sehari-harinya hanya berubah sedikit saja, atau bahkan tidak berubah sama sekali. Hal itu memberi kita gambaran tentang keabadian dan stabilitas; memberi perasaan keteraturan dan ketenangan. Kurang lebih sama halnya dengan masyarakat yang terus berlanjut, seolah tidak bergerak, sementara di dalam diri manusia bermunculan serangkaian kegelisahan dan berbagai perubahan suasana hati.
Jadi, ketika kontak antara pikiran dan hal-hal di sekitar terputus, mental tidak lagi seimbang. Dengan beralih dari satu ruang ke ruang lain, manusia kehilangan kemampuan mengenali objek yang sudah dikenalnya dengan baik, terdampar di lingkungan yang cair dan aneh, dan tak punya referensi apa-apa. Ketika manusia meninggalkan sebuah ruang yang dikenal baik dan beradaptasi di lingkungan baru, manusia akan mengalami periode ketidakpastian yang membuatnya seolah-olah meninggalkan seluruh kepribadiannya.
Hal itulah yang terjadi pada sebagian besar perantauan dan diaspora yang harus tinggal di tempat baru, dengan beragam alasan. Tak sekadar pertimbangan soal kenyamanan dan estetika, tempat yang dianggap rumah telah merekam jejak manusia yang tinggal di dalamnya. Segala rupa furnitur, penataan dan dekorasi ruangan, juga kebiasaan perilaku dan adat istiadat akan mengingatkan kita pada keluarga dan teman; orang-orang terdekat. Pada akhirnya kita terikat padanya, pada kelompok, pada masyarakat tertentu.
Namun, segala furnitur, ornamen, gambar, peralatan, dan pernak-pernik itu juga merupakan topik evaluasi dan perbandingan, memberikan kita wawasan tentang arah baru mode dan selera, dan mengingatkan kita pada kebiasaan lama dan perbedaan sosial. Ini terjadi pada siapa saja, pada saya, pada penulis seperti yang diutarakannya dalam “Nyanyi Sunyi”. Sebagai seorang yang eksploratif, saya punya semacam pegangan untuk meredakan kekhawatiran: kalau datang ke suatu ruang baru, mau tidak mau kau akan membandingkannya dengan ruang sejenis sebelumnya; kalau kau bertemu seseorang baru, mau tidak mau kau akan membandingkannya dengan seseorang yang pernah ditemui sebelumnya. Itu sesuatu yang lumrah dan alamiah.
Membaca “Nyanyi Sunyi” sedikit banyak menggambarkan positivitas pada eksplorasi manusia. “Aku”, sebagaimana sang penulis menyebut dirinya, harus melepaskan keterikatan dengan masa muda dan keluarga di Palembang, tanah yang berbau kematian, kehidupan, juga nenek moyang. Akar tanah, akar hidupku (hal. 32).
Ada ruang-ruang menarik yang dihadirkan penulis pada bagian yang bercerita soal kampung halaman dan keluarga—baik sebagai ruang fisik yang nyata, maupun simbol dan pengantar untuk membicarakan perkara mentalitas. Misalnya, pohon belimbing di halaman rumah. Pohon itu diam-diam bicara tentang kultur patriarki yang menihilkan perempuan (hal. 34), bagaimana pandangan dan harapan masyarakat setempat terhadap perempuan dan laki-laki. Sebagai seorang yang hidup di keluarga Batak, penulis mendapati dirinya hadir di tengah masyarakat tempat anak laki-laki lebih berharga daripada anak perempuan. Anak laki-laki meneruskan marganya, sedangkan anak perempuan lenyap karena ikut suami (hal. 35).
Ruang lainnya adalah rumah masa kecil, sebuah perlambang kemakmuran, sekaligus juga tempat pertama kali yang mengenalkan penulis pada kebiasaan berbohong. Semua orang tentu punya kebohongannya masing-masing, baik kebohongan dengan tujuan baik, maupun sebaliknya. Pada titik tertentu, aku akan berdamai dengan kebohongan-kebohongan itu, atau yang lebih buruk, aku akan beradaptasi sedemikian rupa untuk pada akhirnya merasa cukup nyaman dengan kebohongan yang aku ciptakan sendiri (hal. 51). Penulis, dan mungkin juga kita, mengakui bahwa selalu ada tarik menarik antara cinta dan benci dalam memahami rumah sebagai ruang utama.
Contoh tegangan cinta dan benci pada sebuah ruang juga bisa dibaca dalam bagian yang membahas Jakarta. Hubungan cinta dan benci dengan Jakarta ini sungguh kuat; kadang membingungkan dan membuat aku frustrasi (hal. 60). Jakarta diceritakan bukan sekadar ruang fisik. Ia adalah kota yang mengikat, yang hadir satu set bersama keajaiban tindak-tanduk para penghuninya dan kenangan bersama kekasih.
Pohon belimbing, rumah masa kecil, dan Jakarta adalah beberapa bentuk yang hadir untuk ditafsirkan. Ruang-ruang itu pasti bicara dengan bahasa berbeda pada pembaca. Esai-esai personal ini secara fragmentaris memberi urgensi kehadiran masing-masing ruang itu. Penulis terus bertransformasi, preferensi sosial dan kebiasaannya berubah, kesan dan ingatannya terhadap pohon belimbing, rumah masa kecil, dan kota Jakarta yang imobil tetap mendominasi untuk waktu yang lama. Kalau boleh saya menyebutnya sebagai kelembaman, ruang-ruang fisik itu menentang atau menghambat perubahan di dalam catatan sejarah hidup penulis. Bahkan sampai ia datang dan menetap di Amerika. Apalagi ternyata Amerika tidak seindah dalam bayangan. Aku merasa dicurangi karena ternyata manusia dan segala sesuatunya tidak seindah yang kubayangkan di negeri yang menawarkan kebebasan (hal. 94). Amerika tak ‘seliberal’ yang aku bayangkan (hal. 92 dan 159).
Peralihan dari satu ruang ke ruang lainnya itu menciptakan refleksi terhadap ruang mental semacam itu: ketika realita tak sesuai ekspektasi; ketika hal-hal yang awalnya ingin dihindari kemudian malah justru dirindukan. Rindu tanah air, terutama Jakarta. Keterpaksaan menerima identitas baru. Rindu ibu (hal. 89). Belum lagi dengan perubahan yang sangat cepat: migrasi ke Amerika Serikat, menikah, dan tak lama setelah menikah: hamil (hal. 132). Setelah anak pertama lahir, 19 bulan kemudian aku hamil, tak hanya satu janin, tetapi kembar perempuan (hal. 134). Depresi dan kesepian, baby blues syndrome, post-partum depression, kehilangan romantisme dengan suami, terjadi bertubi-tubi pada satu tubuh. Sebuah negara yang besar namanya serta besar harapan yang disematkan padanya itu, sebagai sebuah ruang fisik, telah mengguncang ruang mental penulis.
Dari Obama hingga Pearl S. Buck
Aku merasa keluar dari penjara masyarakat Indonesia yang mendorong perempuan untuk segera menikah, tapi lantas terjebak dalam kultur Amerika yang kebebasan diekspresikan tak hanya lewat gaya berpakaian tapi juga kebebasan untuk menarik picu senjata api (hal. 94). Citra Amerika sebagai ruang yang dibayangkan untuk waktu lama, runtuh. Ia tak lagi tertutup dalam kerangka yang dibangun selama ini. Mau tidak mau, para diaspora, termasuk penulis, harus beradaptasi dengan lingkungan fisik dan dengan gagasan masyarakat tentangnya.
Namun kehadiran sosok-sosok bisa meningkatkan intensitas perasaan seseorang pada ruang. Di buku ini, mulai dari Barack Obama hingga Pearl S. Buck. Perkara Obama adalah satu hal yang sangat ingin saya tulis di sini. Pengalaman penulis yang ditulis di esai 9/11 dan Risiko Mengabaikan Pandangan Politik Saat Kencan (hal. 85-94) menurut saya lucu dan menyenangkan. Pada pemilu Amerika tahun 2008, penulis secara aktif mendukung pencalonan Obama menjadi presiden, tanpa menyadari bahwa suaminya terdaftar sebagai anggota Partai Republik! Juga pertengkaran mengenai rasisme dan kultur senjata api. Ditambah pula kekagetan tentang fakta bahwa budaya Barat yang dianggap bebas tentang tinggal bersama sebelum menikah atau pernikahan sesama jenis, ternyata tidak sesignifikan itu. Hal-hal itu dibahas dengan cara yang dekat dengan penulis.
Pearl S. Buck adalah sosok yang lain. Esai Selama Aku Tinggal di Rumah Sastrawan Peraih Nobel (hal. 123-128) dan Rumah Kedua di Ithaca (hal. 149-154) memberi intensitas dan intimasi berbeda pada aspek keruangan di buku ini. Kota kecil Ithaca menjadi sangat besar dan megah karena penulis tinggal di rumah Pearl S. Buck pernah tinggal, tepat di pinggir kampus Cornell University. Menurut saya, membayangkan aktivitas dan perasaan Pearl S. Buck ketika tinggal di rumah itu merupakan cara yang romantis untuk menggambarkan keterikatan manusia pada ruang dan lingkungannya, pada Ithaca: kota yang jauh dari kemolekan artifisial ala kota-kota metropolitan—ia cantik tanpa usaha berlebihan (hal. 154).
Gambaran penulis tentang Ithaca dan kota-kota lain di Amerika: Arizona, New York, dan Las Vegas, membentuk gambaran tentang ruang-ruang dan kelembamannya. Saya melihat bahwa buku ini bukan terutama memperlihatkan individu yang terisolasi, melainkan individu sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada sifat material ruang serta berbagi ketetapan dengannya. Kota-kota itu tidak seperti papan tulis yang membebaskan seseorang menulis dan/atau menghapus gambar di atasnya sesuka hati. Sosok atau kelompok tertentu serta aktivitas di dalamnya dapat membangkitkan pemikiran tentang tempat atau ruang tertentu. Mungkin itu alasan mengapa seseorang bisa tak begitu peduli di kota mana ia berada, asalkan bisa berada di pelukan orang yang dicintainya. Ya, cinta itu mengikat, tapi ia takkan begitu tanpa ruang.
Di sebuah ruang, manusia bisa sangat betah berada di situ, juga bisa sangat ingin pergi dari situ selekas-lekasnya, atau di antara keduanya, serasa menapak di dua dunia (hal. 161), seperti yang dikisahkan penulis ketika membicarakan Indonesia dan Amerika.
Relasi cinta dan benci pada Indonesia dan Amerika adalah berarti upaya menemukan keseimbangan di tengah ruang dan segala peralihan. Upaya yang terdengar politis itu mungkin sama besarnya dengan romantika personal penulis dalam Suka Duka Merawat Cinta. Esai itu berisi pembahasan soal problem hidup bersama dan pernikahan, sesuatu yang penting dan tidak boleh luput diceritakan. Sejak kata ‘cinta’ tertera di judul buku, ia terus menjadi penuntun. Dan yang terpenting, ia diungkapkan secara jujur.
Referensi:
https://www.dw.com/id/nyanyi-sunyi-uly-siregar-dan-segala-kesepian-dalam-kejujuran/a-64911002
Coser, L. A. (1977). Masters of Sociological Thought: Ideas of Historical and Social Context (2nd ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Halbwach, Maurice (1950). The Collective Memory. New York: Harper Colophon Books.